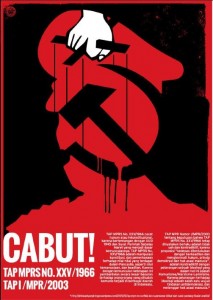24 April 2014 | Hersri Setiawan
Penjara Salemba, 1966, foto: Co Rentmeester, LIFE.
RTC Salemba Jakarta
Rumah Penjara (RP) Salemba atau Lembaga Pemasyarakatan (LP) Salemba
ialah sebutan awam untuk rumah penjara yang terletak di Jalan Salemba Tengah
Jakarta Pusat. Awam lalu biasa menamakan Rumah Penjara atau Lembaga
Pemasyarakatan yang terletak di Jalan Salemba ini dengan sebutannya yang lebih
singkat, yaitu “Penjara Salemba”.
Pada pagi buta
tanggal 1 Oktober 1965 terjadilah peristiwa berdarah di ibukota, yang dipicu
oleh gerakan yang menamakan dirinya “Gerakan 30 September”. Enam orang jenderal
dan satu orang perwira pertama Angkatan Darat tewas pada peristiwa itu. Pada
tanggal 3 Oktober jenazah mereka ditemukan dan diangkat dari sebuah sumur mati
di Lubang Buaya, sebuah desa tidak jauh dari lapangan udara AURI, Halim
Perdanakusumah, dan bertepatan dengan Hari Angkatan Perang tanggal 5 Oktober
1965 jenazah-jenazah itu dimakamkan di Taman Pahlawan “Kalibata” Jakarta
Selatan. Satu-dua hari sesudah itu Jakarta dibersihkan dari “oknum-oknum” G30S,
komunis, dan yang dikomuniskan.
Penjara Salemba tiba-tiba menjadi penuh-sesak dengan tahanan politik atau
tapol. Barangkali pada saat itu jugalah perbendaharaan kata bahasa Indonesia
mendapat satu entri tambahan: “tahanan politik” atau “tapol”. Sudah banyak
peristiwa-peristiwa politik sebelumnya, yang mengakibatkan penangkapan dan
penahanan terhadap “orang-orang politik” tertentu. Namun mereka itu tidak
mendapat sebutan “tahanan politik” atau “tapol”, melainkan disebut dengan
menunjuk pada kasus yang melibatkan “orang politik” itu. Misalnya: “Tahanan
Digul”, “Tahanan 3 Juli”, “Tahanan DI/TII”, ”Tahanan Madiun” dan sebagainya.
“Penjara Salemba” lalu berganti peranan. Tidak lagi menjadi tempat
pengucilan atau pemenjaraan “pesakitan”, “penjahat”, atau kriminal, tapi
dipakai sebagai tempat khusus untuk menahan para “penjahat politik”. Ia lalu
menjadi “Rumah Tahanan Chusus” untuk para “penjahat politik”, yaitu orang-orang
yang dianggap terlibat atau dicurigai terlibat dalam “Peristiwa G30S/PKI”.
Sejak itu ia pun mendapat nama baru: “RTC Salemba”. Penghuninya bukan kriminal
tapi tapol. Adapun penghuni lama “Salemba”, yaitu para kriminal yang sekitar
400 orang itu, konon dipindah ke penjara Glodok di Jakarta Utara.
Penjara Salemba, 1966, foto: Co Rentmeester, LIFE.
Sejak dipakai sebagai tempat penahanan tapol, saking banyaknya “oknum
yang terlibat” dan “yang berindikasi”[1], RTC Salemba lalu menjadi benar-benar
penuh-sesak. Ada sekitar 3000-4000 tapol ditahan di penjara ini. Itu berarti
sepuluh kali lipat, atau bahkan mungkin lebih, dari daya-tampung penjara yang
paling besar di Jakarta ini. Sel-sel di setiap blok yang semula diisi tahanan
kriminal 3 atau maksimum 4 orang, kemudian diisi dengan 7 orang dan bahkan
terkadang sampai 9-11orang tapol. Blok “G” dan “I” yang tidak terdiri dari
sel-sel melainkan berupa satu ruangan besar, karena dahulu berfungsi sebagai
blok tempat tahanan dan narapidana harus bekerja merajin dan berolahraga,
kemudian diubah menjadi “kamar besar” dan masing-masing diisi dengan sekitar
200 orang tapol atau bahkan lebih. Di “kamar besar”[2] ini masing-masing tapol
mendapat bagian jatah kapling[3] seluas lk. 1x 2 meter, berderet-deret
sepanjang tembok blok, dan ruang di tengah pun masih dibagi-bagi lagi dalam
tiga jalur kapling-kapling.
Kecuali tapol yang berjumlah ribuan itu, di RTC Salemba masih disisakan
belasan orang tahanan-kriminil-militer (takrim) di blok khusus, yaitu Blok “E”.
Desas-desus mengatakan, takrim yang disisakan ini adalah takrim-takrim gembong,
yang sengaja dipakai penguasa kamp untuk membantu mengawasi dan mengintimidasi
tapol. Blok “E” dipimpin oleh dua takrim eks-perwira pertama AD, Johny Ayal dan
Syahbandar, di mana ditahan tapol sipil berstatus isolasi berat, seperti halnya
blok “N” yang merupakan tempat isolasi berat untuk “tamil” atau tapol militer.
Bangunan RTC Salemba berbentuk tapal kuda, dengan di tengah-tengah
berupa lapangan yang berfungsi banyak, terutama dan pertama-tama digunakan
sebagai tempat apel para tawanan dan tempat tapol muslim melakukan salat jumat.
Kantor administrasi, ruang pemeriksaan, dapur dan gudang, terletak berderet di
depan pada ruangan di antara dua ujung lingkaran tapal kuda. Semuanya terletak
pada lingkar-kedua bangunan tapal-kuda. Juga termasuk dalam lingkar ini blok
“A” dan blok “B” yang dihuni tapol pekerja RTC. Di antara kewajiban mereka itu,
misalnya, membuka dan menutup pintu blok dan sel, menyiapkan makan dan minum
tapol, membagi air minum dan jatah makan ke blok-blok, merawat kebun bayam di
antara dua tembok tinggi di sekeliling bangunan RTC, mengantar tas besukan dari
keluarga kepada tapol yang bersangkutan, meneruskan perintah penguasa ke
kepala-kepala blok atau tapol, dan tugas-tugas lain-lain lagi. Pada lingkar
ketiga ialah blok-blok RTC, yang terdiri dari sekian banyak sel-sel atau “kamar
kecil”, yang jumlahnya tidak sama antara blok satu dengan lainnya. Selain
blok-blok itu ada lagi blok “RS”, yaitu “blok” khusus rumahsakit penjara.
Sesudah dipindah dari tahanan operasional di Paskoarma II Cilandak ke
RTC Salemba pada 1970, satu tahun kemudian aku akhirnya dipindah ke Pulau Buru,
sebagai terminal terakhir bagi tapol G30S. Selama hampir dua tahun di “Salemba”
aku berpindah-pindah dari blok satu ke blok lain, dan yang terakhir – yaitu
sampai berangkat ke Buru bulan Agustus 1971 – aku menjadi penghuni blok “I”.
Sebelum itu aku pernah menjadi penghuni blok “G” dan blok “F”, serta blok-blok
isolasi “D” dan “E”.
“Slamat datang, pak Her!” Suara dari sel sebelah selku di blok “D”
menyambut kedatanganku.
Aku kenal benar suara parau itu. Ia tentu Pak Slamet Parto, penderita parah
penyakit asma, kawanku setahanan di Paskoarma II Cilandak. Ia keponakan
Jenderal Hartono, panglima Kko-AL, yang pada ujung tahun 1960-an terkenal
dengan ucapan kesetiaannya pada Bung Karno: “Merah kata Bung Karno, merah
tindakan KKo; putih kata Bung Karno, putih tindakan KKo!”.
“Kang! Sampeyan gembong Tebet Timur, kan?” Suara dari sel sebelah Slamet Parto.
“Itu mas Naryo, ya?” Jawabku.
Ia tertawa. Yang kusapa “Mas Naryo” ini anggota PGT (Pasukan Gerak Tjepat)
AURI, berpangkat sersan mayor, tetanggaku satu RT di Kelurahan Tebet Timur.
“Bung!” Suara menyapa dari sel lain lagi. “Aku Saleh Semarang.”
“Bung Saleh, Pekunden!?” Tanyaku. “Kenapa Bung di sini?”
“Aku sudah lama di Jakarta. Tidak di Lekra lagi. Aku di DPP SBKB.[4] Bung kok
pinter sembunyi, sih?”
Aku diam. Tidak mengerti arah pertanyaannya itu. Sekilas ingatanku kembali ke
masa-masa sekian tahun lalu di Semarang.
“Bung sudah lama lho dicari-cari Marjuki …” Suara Saleh lagi. Yang dimaksud
Marjuki ialah Lettu CPM Marjuki, Komandan Kamp Salemba.
“Istirahat dulu, pak Her!” Suara Slamet Parto lagi yang terdengar. “Di sini
lain dari Cilandak lho pak. Semuanya lain! Jangan kaget, ya pak!”
Semuanya lain! Ya, Slamet Parto benar. Tadi ketika aku dibawa masuk ke lingkar
paling dalam bangunan RTC, yang terdengar pertama ialah suara-suara banyak
orang membaca Al Kuran dari seluruh penjuru. Suasana RTC Salemba pada saat-saat
menjelang waktu salat, barangkali mirip seperti suasana di pondok pesantren.
Suara-suara orang membaca ayat-ayat Kuran, sendiri-sendiri atau bersama-sama,
terdengar dari pagi sampai lepas waktu lohor. Kemudian nanti terdengar lagi pada
waktu sekitar salat asar, dan terlebih-lebih pada saat antara salat magrib dan
isyak.
Juga di RTC Salemba ukuran sel lebih sempit dibanding dengan di Paskoarma II.
Lantai dan dinding sel tampak kotor dan tidak terurus. Jeruji-jeruji pintu besi
dan jendela sudah dimakan karat. Bau anyir dan pengap tercium tajam. Apakah
memang seperti ini merupakan pemandangan dan keadaan yang lumrah di semua rumah
penjara?
Aku hamparkan tikar yang kubawa dari Cilandak, dan mencoba beristirahat seperti
anjuran Slamet Parto. Selagi aku masih berbaring dan hanyut dalam pengembaraan
batin, suara petugas korve kudengar.
“Makan, mas!” Katanya.
Piring aluminium yang tidak keruan lagi bentuknya kulihat disorongkan di bawah
pintu. Kuah sayur berwarna kehijauan merendam sedikit nasi di tengah piring.
“Rantang atau cangkirnya, mas!?” Pintanya sambil mengulurkan tangannya dari
antara jeruji pintu.
Kuberikan satu rantang dan satu cangkir.

Penjara Salemba, 1966, foto: Co Rentmeester, LIFE.
Ia memberikannya kembali kepadaku, sesudah mengisi kedua-duanya dengan
air minum. Air matang tentu saja di mana-mana sama. Sama warnanya, dan sama
juga baunya. Maka tanpa kulihat dan kucium rantang dan cangkir berisi air minum
itu kutaruh di lantai begitu saja. Barangkali, pikirku, inilah jatah air-minum
untuk sepanjang hari dan malam nanti.
Penjara Salemba, 1966, foto: Co Rentmeester, LIFE.
Aku terpikir untuk makan. Tadi pagi, ketika aku dipindah dari Paskoarma,
dan singgah di markas CPM di Jalan Guntur Manggarai, jatah makan pagi kami
belum dibagikan. Tapi, seketika memegang bibir piring aluminium itu, aku
tersentak jijik. Licin! Dan ketika sepiring nasi berkuah dengan satu-dua lembar
daun bayam itu kuangkat, kudekatkan ke hidung, tercium bau anyir yang luar
biasa. Kupikir piring itu tidak pernah selamanya dicuci dengan sabun, melainkan
sekedar dilempar-lemparkan masuk ke dalam drum pencucian, lalu diangkat
satu-satu atau sebanyak sebisanya tangan mengangkat, dan ditumpuk di dapur.
Selain licin dan anyir, piring itu pun sudah tidak punya bentuk lagi. Sobek
pada bibirnya di sana-sini, dan juga penyok-penyok tidak keruan.
Piring berikut nasi-sayur jatahku kusorongkan kembali, keluar dari bawah
pintu sel. Utuh, tanpa kusentuh.
“Makan dong, pak!” Suara Slamet Parto. Barangkali ia mendengar suara piring
yang kusorongkan di lantai itu.
“Jangan pakai selera, pak. Pakai kepala!” Ia menasihati. “Tutup hidung setiap
menyuap, pak. Saya dulu juga begitu …”
“Ya, saya akan coba.” Jawabku membohong.
“Ya, makan! Paksa saja, pak! Kalau sakit tambah susah kita …”
Nasihat Slamet Parto tentu saja sangat benar. Tapi aku juga benar-benar
tidak atau belum bisa memenuhi nasihatnya itu. Baru ketika jari menyentuh
piring yang terasa sangat licin itu, belum lagi kuangkat hendak kucium,
perasaan jijik dan mual menggelegak di perut. Aku harus menahan muntah.
Keadaan demikian terus-menerus kualami selama tiga hari. Artinya selama tiga hari
itu juga perutku tidak pernah kemasukan apa pun selain air. Akibatnya, persis
seperti dikatakan Slamet Parto, aku jatuh sakit. Demam tinggi. Dan aku menjadi
semakin tidak mempunyai nafsu makan. Tapi aku tidak ingin mati kelaparan.
Ketika masih di luar, pada tahun-tahun 1967-68, kudengar hampir setiap hari
rata-rata 7-8 orang kawan mati di RTC Salemba. Kebanyakan karena busunglapar.
Nasihat Slamet Parto harus kupaksakan sendiri. Aku harus makan dengan
kepala, dan tidak dengan lidah dan hidung. Setiap tangan kananku mengantar satu
suap ke mulut, jari-jari tangan kiriku memencet keras-keras cuping
lubang-hidungku. Nasi dan kuah sesendok-bebek aluminium itu pun kumasukkan
dalam-dalam ke pangkal lidah. Tidak di ujung atau tengah lidah, tempat
ujung-ujung saraf perasa berakhir.
“Masih sakit, mas?” Tanya Kepala Blok yang tiba-tiba muncul di balik pintu sel.
“Akh, tinggal lemas saja.” Jawabku. “Tapi sudah tidak demam kok.”
Aku tidak tahu apa-dan-siapa Kepala Blok. Ia seorang yang bersosok jangkung,
berkacamata tebal, dan berkulit gelap.
“Tidak ada sarung atau selimut?”
“Tidak.”
Ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Seperti meyakinkan diri sendiri, bahwa
tidak ada seseorang yang melihatnya. Lalu cepat-cepat ia mengulurkan genggaman
tangannya dari sela jeruji pintu. Dua butir gulamerah. Sesudah memberi isyarat
tutup-mulut dengan jari telunjuk di bibirnya ia pergi. Tanpa kata-kata.
Di RTC Salemba bicara antara sesama tahanan, apalagi bergurau sehingga
menimbulkan suara tertawa, termasuk konsinyes atau larangan utama dan pertama
di antara sekian banyak deretan konsinyes. Maka ketika pagi-pagi pada pukul
enam pintu sel dibuka, tapol segera menghambur ke kamar-kecil bukan saja untuk
membuang hajat, tetapi juga untuk bermacam-macam alasan lainnya lagi. Misalnya,
meledakkan tawa atau menjerit tanpa ada yang ditertawakan atau dijeritkan,
tukar-menukar “info” dengan suara saling berbisik, walaupun “info” itu “hanya”
tentang besukan keluarga yang sudah dua minggu mangkir!
Pada saat pagihari di kamar-kecil itulah tapol bisa merebut kesempatan
di celah kesempitan untuk “berekspresi diri” dan melakukan “kontak sosial”.
Kesempatan kontak-sosial juga bisa dicuri pada waktu tiga puluh menit
“berolahraga”, berjalan cepat mondar-mandir di halaman blok sambil bergandengan
tangan dengan sesama teman dekatnya. Ketika itulah mereka bisa saling berbisik
tentang apa saja, walaupun harus sambil tetap waspada terhadap “pucuk-daun dan
rerumputan yang bergoyang” sekalipun.
Komunikasi antara sesama tawanan merupakan larangan atau “konsinyes”, dalam kosakata
tapol G30S. Karena itu ketika kami diangkut dari Namlea ke pantai Sanleko atau
dermaga Air Mandidi, dengan sloep atau sekoci, kami semua harus berdiri tegak
berimpitan seperti batang-batang kayu. Barang bawaan harus dijunjung di atas
kepala. Ini tentu saja demi alasan sekuriti. Untuk tidak memberi kami
ruang-gerak dan kesempatan saling berbicara sedikit pun. Seketika mendarat di
pantai kami harus turun berlompatan dari sloep, lalu berlari dan segera
membentuk barisan. Tidak boleh ada ruang dan waktu untuk hal-hal yang
dinyatakan sebagai “konsinyes”.
Seribusatu rambu-rambu “konduite” memang diberlakukan ketat pada tapol
sepanjang hari dan malam. Istilah “konduite” adalah sepatah istilah lagi selain
”konsinyes”, yang juga paling banyak diucapkan oleh penguasa kamp dan
cecunguk-cecunguk aparatnya. Seakan-akan “dosa politik” sebagai “tapol
G30S/PKI” akan mudah ditebus dengan tingkah-laku atau konduite baik, yaitu
dengan hidup sebagai “insan pancasilais sejati” melalui jalan yang “diridhoi
Allah”.
Di RTC Salemba tidak ada tapol yang dibolehkan bekerja, kecuali tapol
dari blok “A” dan “B”, seperti di atas sudah disebutkan, yang setiap hari
bertugas di dapur umum dan di kebun sayur sekitar bangunan RTC. Beda dengan
kawan-kawan tapol di RTC Tangerang, yang ketika itu juga termasuk dalam wilayah
Kodam V Jaya. Di sana ada sebagian tapol, sekitar 200-an khususnya yang
muda-muda, setiap hari dipekerjakan di luar penjara. Mereka bekerja untuk, apa
yang disebut sebagai, “Proyek Pertanian Kodam V Jaya”, di desa Cikokol, di
peluaran kota Tangerang, yaitu untuk membuka dan menggarap ladang dan sawah,
masing-masing seluas 25 hektar dan 50 hektar. Hasil panenan sawah dan ladang
ini dimaksud untuk memberi makan pada tapol di seluruh Jakarta yang ribuan
jumlahnya, tetapi dalam praktiknya — seperti yang sudah lazim terjadi, juga
misalnya untuk tapol di Nusakambangan — yang pertama dan utama justru bagi para
penguasa kamp, dan baru sisa kelebihannya menjadi jatah tapol sewilayah Kodam V
Jaya.
Setiap pagi sebelum matahari terbit, tapol-tapol pekerja itu digiring
keluar penjara, dan pada petang hari bersamaan dengan matahari terbenam mereka
digiring kembali ke sel-sel isolasi masing-masing. Kecuali untuk beberapa orang
yang terkena kerja-wajib musiman, seperti jaga tanaman dari kemungkinan
serangan hama, pengatur air saluran dan berbagai jenis kerja korve lainnya.
Tapol G30S sejatinya sudah sejak hari pertama mereka masuk dan menghuni
tempat penahanan tidak boleh bekerja, agar supaya tidak terjadi kontak antara
tapol satu dengan lainnya. Tapi agar supaya mereka tidak mati dilanda wabah
busung-lapar, loket penjara dibuka tiga kali dalam satu minggu untuk menerima
besukan makan-minum keluarga. Di satu-dua tempat penahanan di Surakarta tapol
bahkan “dibebaskan” pada sianghari untuk mencari makan mereka sendiri-sendiri.
Di RTC Salemba bukan hanya soal makan-minum yang “diserahkan” pengurusannya
kepada keluarga masing-masing tapol. Juga jika blok sana atau sini memerlukan
ember atau tali timba, kapur di tembok sel atau dinding blok sudah terlalu
kotor, bohlam di sel sana atau sini putus, cat pintu-jeruji sel atau blok sudah
kusam … semuanya itu diserahkan kepada keluarga tapol dan tapol. Keluarga
diminta agar mengirim kebutuhan apa yang diperlukan, dan tapol di dalam yang
diwajibkan mengerjakannya.
Pengasingan tapol G30S ke Pulau Buru, kupikir, satu dari sekian banyak
alasannya, ialah karena di sana tapol tidak akan “habis” dilanda wabah
busung-lapar. Untuk itu mereka harus mencetak sawah-ladang seluas-luasnya.
Malahan kemudian terbukti, bahwa mereka bukan hanya mampu “menghidupi diri
mereka sendiri. Tapi mereka pertama-tama dan terutama harus ikut membantu
membangun perekonomian daerah, dalam hal ini Maluku Tengah, sambil menciptakan
“nilai-nilai” bagi para pembesar unit-unit Inrehab Pulau Buru.
***
[1] Istilah-istilah “oknum” (sosok, tokoh, seseorang) dan “indikasi”
(petunjuk) yang semula bersifat “netral” itu, sejak Peristiwa G30S mendapat
arti sosial-politik yang tertentu; “oknum” ialah “seseorang yang patut
dicurigai terlibat G30S/PKI”, dan “indikasi” ialah “petunjuk keterlibatan
seseorang pada Peristiwa G30S/PKI”.
[2] Penguasa RTC melarang penggunaan istilah “sel”, dan mewajibkan menggantinya
dengan istilah “kamar”. Alasan yang selalu ditegaskannya, dikaitkan dengan
“pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Suharto yang Pancasilais dan
menjunjung tinggi sila Perikemanusiaan” (sic!).
[3] “Kapling” (Bel.: kavling), petak tanah dengan ukuran luas tertentu; dalam
kosakata tapol G30S ialah “petak” ruang seluas kelambu terpasang yang diperoleh
sebagai “jatah” masing-masing tapol. Kapling inilah lebensraum tapol, tempat ia
bisa “leluasa” berbuat apa saja, juga menyimpan “harta-milik” (ransel goni
berisi satu-dua lembar pakaian) pada bagian atas atau kepala.
[4] Kependekan dari Dewan Pimpinan Pusat Serikat Buruh Kendaraan Bermotor.
Sumber: ArusBawah