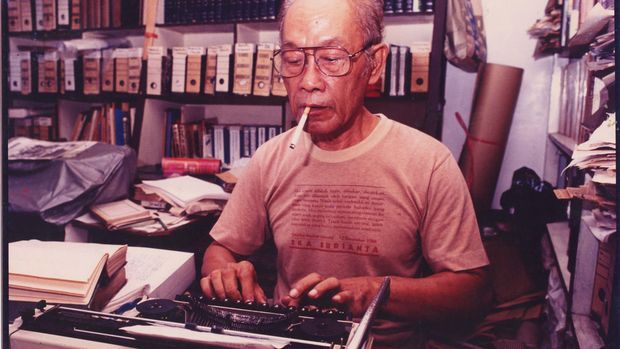Simposium 65 ini merupakan forum yang pertama dalam sejarah indonesia yang penyelenggaraannya disokong dan didukung langsung oleh pemerintah dalam membahas upaya penyelesaian salah satu dari sekian pelanggaran HAM masa lalu. Ahli, pelaku, saksi, korban, dan pengamat dihadirkan dalam acara tersebut untuk berdialog dan berdiskusi mencari titik temu penyelesaian tragedi 1965. Dukungan tersebut membuat penyelenggaran simposium nasional 1965 yang diadakan pada tanggal 18-19 April 2016 di Jakarta berhasil dilaksanakan.
Sepenggal Kisah Korban 1965
Bu Christina Sumarmiyati atau akrab disapa Bu Mami merupakan salah satu korban 1965 yang hadir sebagai pemantik diskusi MAP Corner-klub MKP UGM pada 26 April 2016. Wanita paruh baya itu mengawali diskusi dengan menceritakan pengalamannya sebagai korban tragedi 1965. Saat ditangkap atau diculik oleh militer, beliau baru berumur 21 tahun dan merupakan seorang mahasiswa tingkat 2 (semester 2) di Universitas Gadjah Mada (UGM). Penculikan tersebut terjadi saat beliau pulang dari kampus, dan tiba-tiba ada mobil yang berhenti persis didepannya dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil tanpa memberi alasan. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1965 dan Bu Mami ditahan tanpa proses peradilan, kemudian beliau baru dibebaskan pada tahun 1978.
Selama Bu Mami ditahan, beliau tidak tahu apa kesalahan yang dia perbuat. Beliau dipisahkan dengan keluargannya kemudian dihukum tanpa proses peradilan. Dalam diskusi tersebut beliau bertanya “apa salah kami ” terutama apa salah dia. Pasalnya, Bu Mami selain sebagai seorang mahasiswi, beliau juga merupakan seorang guru agama yang mengajarkan pendidikan agama kepada murid-muridnya. Beliau melemparkan pertanyaan sebagai bahan perenungan “apakah salah jika saya mengajarkan agama kepada murid-murid saya?”. Menurutnya agama mengajarkan tentang kepercayaan terhadap Tuhan, sementara PKI sering diidentikan dengan tidak bertuhan. Propaganda pengiblisan terhadap PKI tersebut terus tertanam berpuluh-puluh tahun sampai sekarang.
Dengan demikian maka konflik yang terjadi pada 1965 disebut sebagai tragedi kemanusiaan. Pendapat tersebut dilontarkan oleh Budiawan (Dosen Kajian Budaya Media UGM) dengan berpedoman pada cerita Bu Mami bahwa banyak orang yang ditangkap, ditahan, dan dibunuh tanpa mengetahui kesalahan yang mereka lakukan dan hal tersebut dilakukan tanpa proses hukum, seperti yang terjadi pada Bu Mami.
Penyelenggaraan simposium 1965: Motif Politis vs Panggilan Moral
Dalam penyelenggaraan simposium 1965 menurut Budiawan terdapat tiga pihak yang berbeda pandangan dalam melihat simposium tersebut. Pertama pihak yang menolak simposium yaitu diwakili oleh aparat atau militer dan kelompok kanan; kedua adalah pihak yang pro simposium, yaitu diwakili oleh aktivis; dan ketiga, pihak yang moderat atau penengah, yaitu diwakili oleh Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres).
Dari ketiga pihak di atas, muncul pertanyaan jika aparat merupakan pihak yang menolak simposium 1965, mengapa Menkopolhukam, Lahut Binjar Panjaitan berada dalam pihak yang seolah-olah pro simposium 65, padahal dia berasal dari militer? Menurut Budiawan ada motif untuk mengkerdilkan tujuan diselenggarakannya simposium 1965. Hal ini berangkat dari statement Luhut ketika membuka acara symposium 65 tersebut, yang menyatakan bahwa pemerintah tidak akan pernah meminta maaf dan mempertanyakan data jumlah korban tragedi 1965. Pernyataan tersebut kemudian direspon oleh berbagai pihak, karena kewenangan rekonsiliasi, pengungkapan kebenaran, dan penegakan hukum ada di tangan presiden bukan Menkopolhukam.
Selain itu, sebelum penyelenggaraan simposium ada keganjilan yang terlihat. Budiawan melihat keganjilan tersebut dari perubahan terhadap para pembicara dalam forum simposium sebanyak 5 kali. Kemudian dari segi substansial materi dapat diprediksi, artinya tidak ada yang baru dan mengejutkan dimana pembicara berasal dari Menkopolhukam, penyintas 1965, dan aktivis HAM.
Harapan pada Simposium 1965 dan Pelajaran dari Tragedi 1965
Menurut Budiawan penyelenggaraan simposium untuk membedah tragedi 1965 yang didukung oleh pemerintah harus dilihat secara bijaksana. Artinya bahwa forum ini harus dilihat sebagai langkah maju untuk mengungkapkan dan menyelesaikan permasalahan HAM masa lalu. Untuk itu, Budiawan mengharapkan forum seperti ini tidak hanya berhenti pada pencarian fakta-fakta belaka, tetapi harus diselenggarakan terus sampai menghasilkan solusi atas permasalahan tersebut sehingga para korban tragedi 1965 dapat hidup dengan tenang tanpa tekanan dan trauma. Selain itu, simposium ini harus menghasilkan pengakuan atas perbuatan yang telah kita lakukan bersama. Senada dengan Budiawan, Bu Mami juga mengharapkan simposium tersebut dapat menghasilkan solusi yang dapat memperbaiki kondisi kehidupan para korban 1965 dan dapat menguak kebenaran dari tragedi 1965.
Menurut Budiawan tragedi 1965 memberikan satu pelajaran yang sangat berharga bagi bangsa indonesia, yaitu ketika kekuasaan terpusat atau terpersonalisasi pada satu orang maka akan memunculkan bahaya yang amat besar. Dengan demikian maka distribusi kekuasaan merupakan hal yang penting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa karena tidak ada monopoli terhadap kebijakan negara atau dengan kata lain sistem demokrasi menjadi sangat penting.
Kekuasaan terpusat pada konteks sebelum tragedi 65 adalah kekuasaan sentral yang berada ditangan Soekarno. Sedangkan PKI dan Militer (terutama AD) menjadi penyeimbang kekuatan yang berada dibandul kiri (PKI) dan kanan (Militer) (Sesuai dengan ide Nasakom Soekarno). Ditengah ketegangan perang dingin dan berita simpang siur tentang jatuh sakitnya Soekarno, muncul pertanyaan tentang kemana tongkat estafet kepemimpinan akan berganti. Disaat itulah muncul aksi yang dilakukan oleh para perwira dengan membunuh 6 jenderal dan 1 perwira tinggi terkait isu Dewan Jendral. Aksi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh kubu kanan untuk mengkambing hitamkan kubu kiri hingga mencuatkan tragedi 65 yang tidak hanya kejahatan kemanusiaan akan tetapi juga penghancuran kapasitas kelas bawah dalam perjuangan politik.
https://www.facebook.com/302809866428471/photos/a.303787282997396.71140.302809866428471/1080687698640680/?type=3&theater