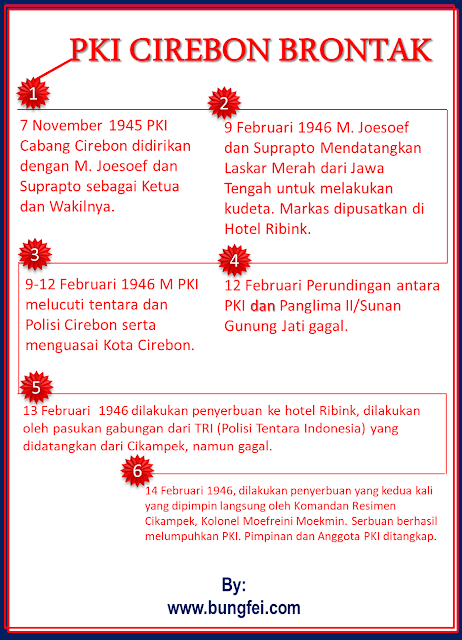Tampilkan postingan dengan label Article. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Article. Tampilkan semua postingan
Minggu, 01 Maret 2020
Semua Adalah PKI
Oleh : Dandhy Dwi Laksono
Seperti halnya 'Genjer-Genjer" yang diciptakan M
Arief, lagu "Garuda Pancasila" juga diciptakan seniman Lekra (Lembaga
Kebudayaan Rakyat). Ia bernama Sudharnoto, pada 1956.
Karena militer dan Orde Baru menganggap Lekra sama dengan
PKI, Sudharnoto yang pernah bekerja di RRI Jakarta kemudian ikut dikejar-kejar
dan dibui. Setelah keluar penjara sekitar 1968-1969, ia bekerja sebagai penjual
es dan sopir taksi. Nasibnya memang sedikit lebih beruntung daripada M Arief
yang hilang setelah peristiwa 30 September.
Di mata Orde Baru, kesalahannya sangat fatal: Menciptakan
lagu "Genjer-Genjer" pada tahun 1942 dengan konteks penderitaan
rakyat menghadapi invasi Jepang, dan lalu lagu itu digemari Njoto (tokoh PKI)
yang sedang singgah ke Banyuwangi.
Lho, apa hubungannya dengan dia sebagai pencipta lagu?
Sejak kapan watak fasis perlu alasan yang masuk akal atas segala sesuatu?
LBH Jakarta dan YLBHI yang secara historis membela semua
kelompok dan ideologi (termasuk kubu Islam garis keras), dihasut sebagai
"sarang PKI" dan diserang.
Patung Tani yang merupakan simbol mobilisasi umum untuk
merebut Papua dari Belanda juga disebut simbol PKI. Buku "Das
Kapital" yang berisi dasar-dasar pemikiran komunisme, justru disebut
"mengajari generasi muda menjadi kapitalis".
Hanya karena sama-sama berjenggot, foto Mikhail Bakunin
yang dicetak di kaos merah salah satu peserta yang datang ke LBH, dikira foto
Karl Marx dan dianggap sebagai bukti keberadaan komunis di acara itu. Padahal
Bakunin penentang komunisme (negara) seperti yang terjadi di Soviet yang
dianggapnya sama menindasnya dengan kapitalisme.
Kelompok fasis yang membalut identitasnya dengan agama
ini bahkan ngotot menyebut Jokowi adalah komunis meski kebijakan dan
proyek-proyek pembangunannya justru sangat kapitalistik dan menimbulkan konflik
di mana-mana, seperti reklamasi Teluk Jakarta, sawah sejuta hektar di Papua
yang akan dikelola perusahaan (bukan rakyat), atau PLTU-PLTU dan bendungannya
yang tidak mencerminkan keadilan ekologis.
Kelompok ini tidak
mau tahu dan tidak peduli.
Jokowi dan Istana tetap disebut mendukung kebangkitan
PKI. Padahal ia tidak merebut dan membagi-bagikan tanah kepada petani seperti
BTI atau PKI. Ia hanya membagi-bagikan sertifikat yang secara jelas menguatkan
konsep kepemilikian pribadi terhadap tanah. Jauh dari ide tanah sebagai faktor
produksi yang harus dikuasai secara komunal.
Dengan disertifikasi, tanah yang milik pribadi, lebih
mudah dibeli dan dikuasai modal, seperti kasus komunitas Sunda Wiwitan di Kuningan,
Jawa Barat. Beda dengan tanah di Baduy Dalam atau Tenganan Pegringsingan di
Karangasem yang tak dapat diperjualbelikan ke pemodal resort atau hotel karena
milik adat.
Jokowi harus disebut PKI. Begitu juga PDIP yang dalam
sejarahnya merupakan fusi partai nasional seperti PNI dan agama (non-Islam).
Meski dalam sejarahnya PNI dan PKI sengit berkonflik (sesengit saling serang
antara koran Suluh Indonesia-PNI dan Harian Rakyat -PKI), tapi gerombolan
ahistoris ini tak peduli.
PDIP dianggap sama dengan komunis. Padahal menjadi
Marhaenis saja, partai ini gagapnya setengah mati. Kader-kadernya seperti
Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, lebih sibuk membela pabrik semen daripada para
petani seperti Pak Marhaen yang sedang mempertahankan sumber air untuk mengairi
sawahnya sendiri yang sepetak-dua petak.
Partai ini bahkan mendukung Basuki "Ahok"
Tjahaja Purnama yang kebijakan pembangunannya menggusur, bahkan dengan
melibatkan tentara. Ahok sendiri adalah pejabat yang dengan enteng menyebut
warga bantaran Waduk Pluit sebagai "komunis", karena dianggap
menduduki "tanah negara".
Tapi bagi kelompok sejenis "massa 299" ini,
semua itu tak penting dan tak relevan. Mereka kawin mawin dengan para jenderal
dan pensiunan yang rindu masa-masa kejayaan Dwifungsi ABRI di era Orde Baru.
Yang bisa memegang tongkat komando, tapi juga bisa duduk di pemerintahan
sebagai pejabat yang mengatur APBN atau APBD. Yang bisa mengerahkan pasukan,
tapi juga bisa duduk di DPR ikut membuat Undang Undang. Yang tetap
mempertahankan baret dan seragamnya, tapi juga bisa duduk di komisaris
perusahaan negara, daerah, dan swasta.
Siapa yang tak rindu masa-masa itu? Dan jalan paling
murah untuk mewujudkannya adalah menggalang sentimen anti-komunisme, dibalut
agama. Karena itu semua harus di-PKI-kan. Semua adalah PKI. Padahal merekalah
yang PKI: Penduduk Kurang Informasi.
***
(Matipa, Refleksi_Menolak Lupa,01-03-2020)Senin, 24 Februari 2020
PKI Cirebon Brontak
Februari 24, 2020
Pemberontakan PKI Cirebon jarang diekspos ke permukaan, padahal pemberontakan PKI di Cirebon adalah pemberontakan tertua selepas diproklamasikannya Kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa pemberontakan tersebut terjadi pada 12 Februari 1946.
PKI Cirebon brontak ketika negara sedang dirundung ketidak pastian, menyerahnya Jepang pada sekutu membuat kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 dibayang-bayangi ketidak pastian, karena diam-diam sekutu menyerahkan kekuasaan Indonesia pada Belanda.
PKI Cirebon brontak ketika negara sedang dirundung ketidak pastian, menyerahnya Jepang pada sekutu membuat kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 dibayang-bayangi ketidak pastian, karena diam-diam sekutu menyerahkan kekuasaan Indonesia pada Belanda.
Ketika Tentara Nasional Indonesia (dahulu TRI) sedang mempersiapkan perlawanan pada Belanda, pada saat itu pula PKI cabang Cirebon justru mengadakan pemberontakan, bahkan pemberontakan tersebut berhasil menguasai Kota Cirebon, sementara Tentara Republik dibuat tak berdaya oleh tentara merah kaum komunis.
PKI Cirebon sebetulnya baru didirikan pada 7 November 1945, sedangkan yang menjadi ketua dan wakilnya adalah Mohamad Joesoef dan Suprapto. Ini artinya pendirian PKI Cabang Cirebon baru dilakukan selepas 3 Bulan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Meskipun begitu, PKI Cabang Cirebon ini rupanya agresif, sebab pemberontakan yang mereka lakukan hanya berselang 3 bulan selepas partai itu membuka cabangnya di Cirebon (7 November 1945-12 Februari 1946).
Pemberontakan PKI di Cirebon didalangi langsung oleh pemimpinnya. Dalam memuluskan aksinya, Mohamad Joesoef dan Suprapto mendatangkan Laskar (tentara) Merah PKI dari Jawa Tengah, tujuan utamanya adalah melakukan kudeta lokal di Cirebon.
Para Laskar Merah PKI tiba di Stasiun Kereta Api Cirebon pada 9 Februari 1946 dengan bersenjata lengkap, selanjutnya setelah dikordinir maka pada 12 Februari 1946 laskar merah PKI menginap di Hotel Ribrink, sekarang hotel tersebut berganti nama menjadi Grand Hotel, berlokasi persis sebelah utara alun-alun Kejaksan. Sesampinya di hotel, mereka menjadikannya sebagai markas pemberontakan.
Pada mulanya, ketika laskar merah PKI baru saja tiba di stasiun, seisi kota Cirebon heboh sebab laskar merah secara terang-terangan menengteng senjata, sehingga kedatangan para milisi PKI tersebut mengagetkan pihak keamaanan republik.
PKI Cirebon sebetulnya baru didirikan pada 7 November 1945, sedangkan yang menjadi ketua dan wakilnya adalah Mohamad Joesoef dan Suprapto. Ini artinya pendirian PKI Cabang Cirebon baru dilakukan selepas 3 Bulan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Meskipun begitu, PKI Cabang Cirebon ini rupanya agresif, sebab pemberontakan yang mereka lakukan hanya berselang 3 bulan selepas partai itu membuka cabangnya di Cirebon (7 November 1945-12 Februari 1946).
Pemberontakan PKI di Cirebon didalangi langsung oleh pemimpinnya. Dalam memuluskan aksinya, Mohamad Joesoef dan Suprapto mendatangkan Laskar (tentara) Merah PKI dari Jawa Tengah, tujuan utamanya adalah melakukan kudeta lokal di Cirebon.
Para Laskar Merah PKI tiba di Stasiun Kereta Api Cirebon pada 9 Februari 1946 dengan bersenjata lengkap, selanjutnya setelah dikordinir maka pada 12 Februari 1946 laskar merah PKI menginap di Hotel Ribrink, sekarang hotel tersebut berganti nama menjadi Grand Hotel, berlokasi persis sebelah utara alun-alun Kejaksan. Sesampinya di hotel, mereka menjadikannya sebagai markas pemberontakan.
Pada mulanya, ketika laskar merah PKI baru saja tiba di stasiun, seisi kota Cirebon heboh sebab laskar merah secara terang-terangan menengteng senjata, sehingga kedatangan para milisi PKI tersebut mengagetkan pihak keamaanan republik.
Letda D Sudarsono selaku Polisi Tentara Cirebon yang mendapat info kedatangan orang-orang bersenjata ke cirebon mendatangi stasiun menemui seorang bintara jaga untuk memastikan kebenaran kabar, namun baru saja sampai di stasiun, Letda D Sedarsono disambut dengan tembakan, Ia dikepung, senjatanya dirampas kemudian ditawan.
Selanjutnya, dalam upaya PKI menguasai pemerintahan, kekuatan bersenjata (TNI-POLRI) di Cirebon dilucuti, tentara ditangkap dan dijadikan tawanan. Kala itu kondisi kota mencekam, seluruh kota dikuasai oleh Laskar Merah. Bahkan tindakan laskar merah semakin brutal, merampok dan menguasai gedung-gedung fital.
Menghadapi ancaman serius yang dilancarkan PKI dengan lascar merahnya, Panglima II/Sunan Gunung Jati, Kolonel Zainal Asikin yang lolos dari penangkapan segera mengambil tindakan. Ia mengirim utusan untuk berunding dengan Mohamad Joesoef di Hotel Ribink. Dalam perundingan tersebut pihak PKI mulanya berjanji akan menyerahkan senjata hasil rampasan esok harinya, tetapi janji tersebut rupanya tidak ditepati.
Karena perundingan gagal, Panglima Divisi II meminta bantuan pasukan dari Komandan Resimen Cikampek untuk dikirim ke Cirebon, maka dikirimlah 600 prajurit Banteng Taruna dipimpin Mayor Banuhadi. Akhirnya pada tanggal 13 Februari 1946 dilakukan penyerbuan yang pertama oleh pasukan gabungan dari TRI (Polisi Tentara Indonesia), yang mana tujuannya merebut Hotel Ribink yang kala itu dijadikan markas PKI.
Selanjutnya, dalam upaya PKI menguasai pemerintahan, kekuatan bersenjata (TNI-POLRI) di Cirebon dilucuti, tentara ditangkap dan dijadikan tawanan. Kala itu kondisi kota mencekam, seluruh kota dikuasai oleh Laskar Merah. Bahkan tindakan laskar merah semakin brutal, merampok dan menguasai gedung-gedung fital.
Menghadapi ancaman serius yang dilancarkan PKI dengan lascar merahnya, Panglima II/Sunan Gunung Jati, Kolonel Zainal Asikin yang lolos dari penangkapan segera mengambil tindakan. Ia mengirim utusan untuk berunding dengan Mohamad Joesoef di Hotel Ribink. Dalam perundingan tersebut pihak PKI mulanya berjanji akan menyerahkan senjata hasil rampasan esok harinya, tetapi janji tersebut rupanya tidak ditepati.
Karena perundingan gagal, Panglima Divisi II meminta bantuan pasukan dari Komandan Resimen Cikampek untuk dikirim ke Cirebon, maka dikirimlah 600 prajurit Banteng Taruna dipimpin Mayor Banuhadi. Akhirnya pada tanggal 13 Februari 1946 dilakukan penyerbuan yang pertama oleh pasukan gabungan dari TRI (Polisi Tentara Indonesia), yang mana tujuannya merebut Hotel Ribink yang kala itu dijadikan markas PKI.
Penyerbuan pertama gagal, karena persenjataan di pihak TRI dan kawan-kawan kurang. Sedangkan senjata musuh lengkap.
Pada 14 Februari 1946, dilakukan penyerbuan yang kedua, oprasi dipimpin langsung oleh Komandan Resimen Cikampek, Kolonel Moefreini Moekmin. Hasilnya, mereka berhasil melumpuhkan PKI , sehingga pasukan PKI menyerah. Pimpinan pemberontak, Mohamad Joesoef dan Suprapto berhasil ditangkap, kemudian diajukan ke pengadilan tentara.
Pada 14 Februari 1946, dilakukan penyerbuan yang kedua, oprasi dipimpin langsung oleh Komandan Resimen Cikampek, Kolonel Moefreini Moekmin. Hasilnya, mereka berhasil melumpuhkan PKI , sehingga pasukan PKI menyerah. Pimpinan pemberontak, Mohamad Joesoef dan Suprapto berhasil ditangkap, kemudian diajukan ke pengadilan tentara.
Meskipun kisah pemberontakan PKI Cirebon ini diakhiri dengan dijebloskanya pimpinan PKI Cirebon, yaitu Mohamad Joesoef dan Suprapto ke pangadilan, namun sejauh ini belum ada kisah lanjutan mengenai nasib keduanya serta nasib para pengikutnya. Mengingat pada masa itu selain menghadapi PKI, negara juga sedang mempersiapkan diri menghadapi agresi militer Belanda.
Zaman Peralihan
Andreas
JW – 24 Februari 2020
Meski sangat singkat, hanya tiga bulan, tapi Muso sempat
mewujudkan beberapa langkah strategis buat partainya. Ia kembali ke Tanah Air
medio Juli 1948, dan gugur akhir Oktober 1948. Diawali dengan mengeluarkan
otokritik Resolusi Jalan Baru, rencana selanjutnya, berlandaskan resolusi ini
akan diadakan kongres fusi tiga parpol, yakni PKI, Partai Sosialis, dan PBI;
menjadi satu partai ML bernama PKI.
Sebenarnya, sebelum kehadiran Muso, PKI dan FDR sudah
mengadakan otokritik, menyusul jatuhnya Kabinet Amir Sjarifuddin. Tapi isi
otokritik tidak cukup mendalam. Meski begitu, beberapa materi kemudian menjadi
bahan masukan Resolusi Jalan Baru.
"Dugaan saya, Alimin dianggap kurang berhasil. Sehingga Kominform memutuskan agar Muso segera pulang," kata Siswoyo.
Sebelum pulang, kabarnya, Muso terlebih dahulu berdiskusi
dengan pimpinan Kominform (sebelumnya Komintern) untuk mengoreksi garis politik
kanan PKI, yang dinilai melemahkan perjuangan nasional Revolusi Agustus 1945.
Dalam diskusi tersebut, yang bertempat di Praha, hadir Sekjen CPN Paul de Grost
dan Ketua PK Cekoslovakia Clement Goswald.
Diskusi menyimpulkan bahwa PKI maupun CPN akan berjuang
membatalkan Perjanjian Linggarjati. Karena, tercapainya Perjanjian Linggarjati,
telah menempatkan RI dan Kerajaan Belanda dalam ikatan Unie Verband, di bawah
kekuasaan Raja Belanda. Sebab itu, harus dibatalkan.
Dalam sidang Pimpinan Pusat FDR, Muso, Drs. Maruto
Darusman, Tan Ling Djie, dan Ngadiman Harjosubroto, masuk dalam formasi
Sekretariat Umum (CC sementara), yang membawahi beberapa departemen.
Adapun Kepala Departemen Pertahanan dipegang Amir
Sjarifuddin, dengan anggota terdiri Mayjen. Ir. Sakirman (Laskar Rakyat/Partai
Buruh), Mayjen. Djokosujono (Kepala Biro Perjuangan RI, Pesindo), Ruslan
Widjajasastra (Ketua Pesindo). Departemen Tani, dikepalai dr. Cokronegoro
(Partai Sosialis), dengan anggota Asmu dan D.N. Aidit. Departemen Buruh terdiri
dari Drs. Setiajid, Djoko Sujono, Achmad Sumadi, serta Harjono. Departemen
Agitprop terdiri dari M.H. Lukman, Alimin, dan Sarjono.
Sedangkan Wikana (Pesindo) menangani Departemen Pemuda.
Departemen Organisasi, dipegang Sudisman. Departemen Luar Negeri, dipercayakan
pada Suripno. Nyoto menangani Departemen Perwakilan. Adapun Departemen
Keuangan/Bendahara, dipercayakan pada Ruskak.
Siapa Maruto Darusman? Ia adalah kader CPN, yang lama
bermukim di Negeri Belanda, dan baru kembali ke Indonesia kira-kira pada awal
Agresi I, sekitar tahun 1947. Sebelum kedatangan Muso, ia berfungsi sebagai
Wakil Ketua, di bawah Ketua CC PKI Sarjono.
Sementara Tan Ling Djie berasal dari Partai Sosialis.
Tidak banyak informasi mengenai sejarah perjuangannya, termasuk bagaimana ia
bisa begitu cepat menjadi tokoh Partai Sosialis dan FDR.
Akan halnya Ngadiman Harjosubroto. Ia Angkatan 1926, dan
pernah dibuang ke Boven Digul, Tanah Merah. Dari Australia, ia pulang ke
Indonesia akhir 1946, bersama dengan Sarjono, Winanta, Dita Wilasta, dan
Suratno. Pada Kongres IV PKI tahun 1947, di Solo, Ngadiman terpilih sebagai
Sekretaris Umum.
"Saya tidak ikut dalam sidang PP FDR. Karena saya hanya salah seorang pimpinan PKI/FDR Karesidenan Surakarta." Meski begitu, lanjut Siswoyo salah seorang pimpinan FDR Pusat pernah memberikan kepadanya notulen lengkap hasil pertemuan tersebut.
Notulen berupa tulisan mesin ketik di
atas kertas doorslag berwarna kuning. Dari notulen ini diketahui ada sejumlah
tokoh FDR yang tidak sepenuhnya menyetujui garis Resolusi Jalan Baru.
Seperti seorang tokoh wanita SK Trimurti dari PBI, ia
justru mengecam PKI tidak mampu memimpin revolusi. Sebaliknya ia cenderung
memuji Tan Malaka. Begitu pun Sumarsono dari Pesindo, mendesak Muso segera
memimpin kudeta guna melancarkan perjuangan. Tapi Muso menolak semua itu, dan
dengan tegas mengatakan bahwa kudeta bukan jalan kaum revolusioner.
Sejarah mencatat, gagalnya penyelenggaraan Kongres Fusi,
merupakan akibat tidak langsung dari terjadinya Peristiwa Madiun, yang
memunculkan sejumlah masalah yang cukup rumit dalam kehidupan organisasi
partai.
Misalnya, secara yuridis formal Resolusi Jalan Baru belum
sah. Sementara itu, menyusul gugurnya Muso dan Maruto Darusman, otomatis Tan
Ling Djie menjadi orang pertama dalam CC Sementara. Padahal dia bukan dari
unsur PKI, tapi dari unsur Partai Sosialis. Ditambah lagi Partai Sosialis
pimpinan Tan Ling Djie belum mengadakan kongres istimewa untuk menghadapi
kongres fusi. Dan Tan Ling Djie sendiri tidak setuju dengan Resolusi Jalan
Baru, dengan alasan belum disahkan oleh Kongres Fusi.
Lalu muncul ide dari Tan Ling Djie bahwa Partai Sosialis
perlu dibangun kembali untuk selanjutnya menyelenggarakan kongres istimewa.
Buktinya, pada medio 1950, seorang utusan PP Partai Sosialis menemui Bung
Istijab, ketua Partai Sosialis Cabang Klaten. Ia diinstruksikan untuk
menghidupkan kembali Partai Sosialis. Dengan tegas Bung Istijab menolak, karena
Partai Sosialis Klaten sudah bubar, dan meleburkan diri ke dalam PKI.
Ide Tan Ling Djie juga ditolak sebagian besar anggota CC
Sementara. Begitu pula sejumlah anggota Partai Sosialis yang berada di
Yogyakarta, di markas PP Partai Sosialis, seperti Oloan Hutapea, Kadaruzaman,
Munir, Hartoyo, dan Yusuf Adjitorop, tidak mendukung ide tersebut.
Sebelumnya, pada akhir 1949 datang utusan CC Sementara,
Djoko Sujono dan Ruslan Wijayasastra, menemui pimpinan SC Surakarta. Dalam
beberapa kali kesempatan diskusi, keduanya tidak pernah mempermasalahkan
Resolusi Jalan Baru. Keduanya tahu, jika dipersoalkan pasti akan ditentang
keras. Keduanya tahu SC yang sependirian dengan SC Surakarta cukup banyak
jumlahnya. Selanjutnya Djoko Sujono menjadi petugas penghubung CC Sementara
dengan SC Surakarta.
Ketika itu partai secara resmi tidak dilarang pemerintah.
Tapi demi keamanan, dilakukan sistem “open office”. Dengan pengertian, ada
kantor resmi SC, tapi yang bekerja sehari-hari bukan pimpinan partai. Sedangkan
kantor yang sesungguhnya berada di tempat lain, dan sifatnya tertutup. Open
office SC Surakarta semula ada di Tipes, lalu pindah ke Jalan Honggowongso.
Sehari-hari dipimpin Pak Suratno, seorang kader Angkatan 26.
Karena sering bertemu, "Hubungan saya dengan Djoko
Sujono menjadi akrab. Dia respek dengan SC Surakarta, terutama karena punya
banyak kader, punya akar di kalangan massa, punya pasukan bersenjata (PSR), dan
banyak simpatisannya berada di TNI. Saya tahu, sebenarnya Djoko Sujono
sependapat dengan pendirian SC Surakarta, daripada dengan Tan Ling Djie,"
papar Siswoyo.
Masalah itu semakin jelas ketika Djoko Sujono datang ke
Solo membawa sejumlah petunjuk kerja dan beberapa instruksi dari CC Sementara.
Isinya berbagai macam soal-soal kecil dan bersifat teknis, justru dibahas
sangat detil, seperti urusan koperasi, usaha kecil, PMI, UU Peraturan
Pemerintah.
Yang mencengangkan, adalah tulisan Tan Ling Djie mengenai
idenya tentang Republik Federal Indonesia. Jalan berpikirnya, karena setelah
terjadi Peristiwa Madiun, NKRI menjadi sebuah negara yang anti-komunis. Ketika
itu Irian Barat belum termasuk wilayah Indonesia. Karena itu PKI perlu
mengerahkan gerakannya masuk ke Irian Barat untuk membentuk Republik Demokrasi
Rakyat Irian Barat, kemudian membentuk Negara Federal dengan Republik
Indonesia. Selanjutnya melalui Republik Federal mengubah NKRI yang anti-komunis
menjadi pro-komunis.
Setelah mempelajari isi dokumen itu, SC Surakarta
menyimpulkan sepenuhnya menolak; karena isinya ruwet, tidak masuk akal, dan
sama sekali tidak realistis. Dan SC Surakarta kembali menegaskan tetap memegang
teguh garis Resolusi Jalan Baru.
Sejak itu SC Surakarta tidak lagi berhubungan dengan CC Sementara
pimpinan Tan Ling Djie, karena ada perkembangan situasi baru yang lebih
penting.
Kira-kira medio 1950 datanglah Bung Aidit dan Lukman dari
Jakarta ke Solo. Setibanya di Solo, Aidit dan Lukman segera mencari Siswoyo
.dan Bung Suhadi alias Pak Karto, kader tua dan salah seorang pimpinan SC
Surakarta. Dalam kesempatan itu Aidit menjelaskan situasi intern CC Sementara.
Antara lain ia mengatakan bahwa terdapat perbedaan besar dalam berbagai soal,
terutama yang menyangkut sikap mengenai Resolusi Jalan Baru. Baik Aidit maupun
Lukman sepenuhnya setuju dengan pendirian SC Surakarta, yang tetap memegang
teguh garis Resolusi Jalan Baru. Aidit juga menjelaskan bahwa CC Sementara
membentuk open office yang dipimpin Sudisman. Dan disepakati hanya berhubungan
dengan open office saja.
Belakangan baru diketahui bahwa sebelum open office
dipindah ke Jakarta, sejumlah kader partai sudah terlebih dahulu dikirim
kesana. Kader-kader dari Yogyakarta ini merintis jaringan partai di Jakarta.
Mereka ialah Munir, Kadaruzaman, Hartoyo, Achmad Sumardi, Iskandar Subekti, dan
lain-lainnya.
Pada akhir tahun 1950 berlangsung Sidang Pleno CC
Sementara. Selain mempertegas berlakunya Resolusi Jalan Baru, juga terjadi
perubahan anggota Politbiro. Komposisinya terdiri dari Ketua D.N. Aidit; Wakil
Ketua M.H. Lukman; Wakil Ketua Nyoto; Sekretaris Sudisman, Alimin, Asmu, Ruslan
Wijayasastra, dan Sakirman. Juga dipromosikan sejumlah kader untuk mengisi
posisi Komisaris CC, yakni Oloan Hutapea untuk Jawa Timur, Suhadi untuk Jawa
Tengah dan DIY, Peris Pardede untuk Jawa Barat dan Ibukota Jakarta, Zaelani
untuk Sumatera Selatan, Bachtarudin untuk Sumatera Tengah, dan Jusuf Ajitorop
untuk Sumatera Utara. Mereka sekaligus dipromosikan sebagai anggota CC. Sidang
Pleno juga memutuskan untuk mendegradasi Tan Ling Djie dan Ngadiman dari
keanggotaan CC.
Tetapi keduanya tetap sebagai anggota partai.
Literasi Sains dan Kemerdekaan Akademis
Farid
Gaban - 24 Februari 2020
Banyak yang belakangan risau tentang maraknya pseudo-science serta menguatnya argumen
agama untuk menjelaskan fenomena sehari-hari.
Renang di kolam bisa membuat perempuan hamil? Virus
corona azab dari Allah dan bisa diobati lewat rukyah?
Orang juga kuatir tentang rendahnya literasi sains di
Indonesia, tak hanya di kalangan orang awam, tapi bahkan juga di kalangan orang
terdidik serta pejabat publik.
Menurutku, Indonesia masa kini sebenarnya sedang menuai
metode cuci otak yang diterapkan di lingkungan akademis (sekolah dan kampus)
sejak 1980-an. Ini merupakan buah dari hancurnya kebebasan akademis serta
ambruknya wibawa mimbar akademis.
Pada era Orde Baru kita mengenal program
"normalisasi kampus", menyusul luasnya demonstrasi mahasiswa
menentang rezim. "Normalisasi kampus" adalah eufemisme dari
"menjinakkan kampus"; supaya mahasiswa tidak melawan pemerintah.
Diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan Daoed Joesoef,
program ini pada prinsipnya mendorong kampus semata menjadi pabrik tenaga
kerja. Daya kritis dan kepekaan sosial mahasiswa dikebiri. Bahkan kemerdekaan
kampus, yang disimbolkan oleh kewibawaan senat gurubesar, juga diruntuhkan.
Mimbar akademis dipancung antara lain dengan cara
menjadikan para rektor dan gurubesar sekadar kepanjangan birokrat Kementerian
Pendidikan. Kebebasan akademis makin luntur. Rektor, yang dulu merupakan
wilayah hak prerogatif senat gurubesar, belakangan ikut dipilih oleh menteri,
dengan selera politik.
Diskusi-diskusi di kampus, termasuk bedah buku dan bedah
kasus, lebih diarahkan pada tema keilmuan sempit atau keprofesian. Terlarang
mendiskusikan politik maupun masalah sosial (seperti penggusuran, ketimpangan,
ketidakadilan dan kerusakan alam).
Mendiskusikan Marxisme, misalnya, diharamkan; sementara
kapitalisme diterima dan diajarkan secara otomatis (by default).
Organisasi serta kegiatan mahasiswa dibatasi ruang
geraknya, hanya yang berkaitan dengan seni, olahraga serta keagamaan. Banyak
aktivis yang kuat aspirasi politik dan peka sosial harus menyuruk ke bawah
tanah, menggunakan wadah-wadah pengajian untuk beraktivitas serta
menyebarluaskan gagasan.
Tidak heran jika bahkan di sekolah dan kampus negeri,
organisasi seperti OSIS digantikan oleh Rohis (remaja Islam), serta dewan
mahasiswa digantikan BEM yang secara umum lebih mewakili aspirasi mahasiswa
Islam saja.
Sejumlah kalangan, termasuk pejabat Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme (BNPT), menyebut banyak universitas terpapar
"paham radikalisme". Bahkan jika ada benarnya, sinyalemen ini keliru
diagnosis.
"Radikalisme" (jika ada) merupakan akibat,
bukan sebab; dia merupakan buah dari hilangnya daya kritis. Fanatisme adalah
kawan karib dari keengganan berdialog serta menguji kritis pandangan seseorang.
Dan fanatisme (bukan hanya berbasis agama, tapi juga
fanatisme politik) tumbuh subur ketika kampus sendiri kehilangan kebebasan
ilmiah/akademis.
Polarisasi politik kampus atas dasar suka-tak-suka
politisi idola adalah salah satu wujud ambruknya pertimbangan-pertimbangan
ilmiah.
Bermula pada masa Orde Baru, "penjinakan
kampus" berlanjut ke era Reformasi. Bahkan ketika hari-hari ini Menteri
Pendidikan hanya cenderung melihat kampus sebagai pabrik tenaga kerja belaka.
Dulu kampus tunduk pada politik (Orde Baru), kini tunduk
para kekuasan kapital (korporat).
Runtuhnya kebebasan akademis di kampus bukan cuma
kesalahan birokrat pemerintah. Tapi, juga para gurubesar yang rela
kewibawaannya ditempatkan di bawah selera politik dan birokrasi.
Atau lebih konyol, para dosen dan profesor yang pada
dasarnya merupakan hasil dirikan era Orde Baru itu, ikut-ikutan memberangus
daya kritis serta kepekaan sosial para mahasiswa.
Membicarakan literasi sains harus dimulai dari menegakkan
kembali kewibawaan kampus sebagai lembaga ilmiah yang punya kemerdekaan
akademis.
***
Jumat, 14 Februari 2020
Kolonialisme, Penyebab Tersembunyi Dari Krisis Lingkungan Kita
2020-02-14
Budak memotong tebu di Antigua - British Library
Greta Thunberg memanfaatkan bidang beasiswa yang berkembang ketika dia menulis baru-baru ini bahwa untuk menyelamatkan planet ini, pertama-tama kita perlu membongkar "sistem penindasan kolonial, rasis, dan patriarkal."
-Analisis-
PARIS - Mereka mungkin hanya beberapa kalimat pendek, tetapi mereka telah memicu reaksi keras di antara kritikus Greta Thunberg , remaja Swedia yang menjadi tokoh bagi gerakan iklim.
Pada 9 November 2019, sebuah artikel berjudul "Mengapa kita menyerang lagi," yang ditulis oleh Thunberg dan dua lainnya, menyatakan, "Krisis iklim bukan hanya tentang lingkungan. Itu adalah krisis hak asasi manusia, keadilan, dan kemauan politik. Sistem penindasan kolonial, rasis, dan patriarki telah menciptakan dan mengobarkannya. Kita perlu membongkar semuanya. Para pemimpin politik kita tidak lagi bisa mengelak dari tanggung jawab mereka. "
Artikel ini mengambil salah satu argumen dari lingkunganisme de-kolonial: bahwa krisis iklim terkait dengan sejarah perbudakan dan kolonialisme oleh kekuatan-kekuatan Barat.
Sejak tahun 1970-an, peneliti Afrika-Amerika telah membuat hubungan antara lingkungan dan kolonialisme.
"Solusi nyata untuk krisis lingkungan adalah dekolonisasi ras kulit hitam," tulis Nathan Hare pada tahun 1970.
Lima tahun kemudian, sosiolog Terry Jones berbicara tentang "ekologi apartheid," sebuah konsep yang akan dikembangkan lebih lanjut pada 1990-an oleh Amerika Latin pemikir dekolonial di universitas-universitas Amerika, seperti Walter Mignolo di Duke (North Carolina), Ramón Grosfoguel di Berkeley (California) atau Arturo Escobar di University of North Carolina.
"Awal asli Anthropocene adalah kolonisasi Eropa di Amerika. Peristiwa bersejarah besar ini, yang memiliki konsekuensi dramatis bagi penduduk asli Amerika dan mendirikan ekonomi dunia kapitalis, juga telah meninggalkan jejaknya pada geologi planet kita," tulis peneliti Christophe Bonneuil dan Jean-Baptiste Fressoz dalam The Shock of the Anthropocene: The Earth, History and Us , menyinggung karya ahli geografi Inggris Simon Lewis dan Mark Maslin. "
"Menyatukan flora dan fauna dari Dunia Lama dan Dunia Baru benar-benar mengubah pertanian, botani, dan zoologi di seluruh dunia, dengan bentuk kehidupan yang telah dipisahkan oleh perpecahan Pangaea dan penciptaan Samudra Atlantik 200 juta tahun sebelum tiba-tiba bercampur sekali lagi," tambah mereka.
Di Prancis, para peneliti berusaha untuk menunjukkan bagaimana perdagangan budak, perbudakan dan penaklukan dan eksploitasi koloni memungkinkan kapitalisme menjadi terstruktur di sekitar ekonomi ekstraksi. Cara destruktif untuk menghuni planet kita ini bertanggung jawab untuk mengantarkan zaman geologis baru yang ditandai oleh aktivitas industri manusia: Anthropocene.
Bagi para pemikir dekolonial, bukanlah manusia (antropos) yang bertanggung jawab atas perubahan iklim, tetapi jenis aktivitas manusia tertentu yang terkait dengan kapitalisme Barat. Mereka mengklaim bahwa krisis lingkungan saat ini merupakan konsekuensi langsung dari sejarah kolonial.
Memetik kapas di perkebunan di Selatan pada tahun 1913 - Foto: Jerome H. Farbar
Populasi negara-negara yang kurang berkembang secara ekonomi tidak bertanggung jawab, tetapi merekalah yang menderita. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan oleh jurnal Amerika PNAS pada Mei 2019, pakar iklim Noah Diffenbaugh mengklaim bahwa "sebagian besar negara miskin di Bumi jauh lebih miskin daripada yang seharusnya tanpa pemanasan global. Pada saat yang sama, sebagian besar negara kaya lebih kaya dari yang seharusnya."
Untuk menyoroti bagaimana akar krisis iklim terletak pada perbudakan dan kolonialisme, peneliti Donna Haraway, Nils Bubandt, dan Anna Tsing menciptakan istilah "perkebunan".
"Ini menggambarkan transformasi yang menghancurkan dari berbagai jenis padang rumput, budaya dan hutan menjadi perkebunan tertutup, ekstraktif, yang didirikan pada karya budak dan bentuk-bentuk pekerjaan lain yang melibatkan eksploitasi, alienasi dan perpindahan spasial secara umum," Donna Haraway menjelaskan dalam sebuah Wawancara 2019 dengan Le Monde .
"[Ini mengingatkan kita bahwa] model ini membangun perkebunan secara besar-besaran didahului kapitalisme industri dan memungkinkan untuk mengembangkan, mengumpulkan kekayaan di belakang manusia direduksi menjadi perbudakan. Dari 15 th sampai 19 th abad, tebu perkebunan di Brasil, saat itu di Karibia, terkait erat dengan perkembangan merkantilisme dan kolonialisme."
Kami mengeksploitasi tanah dan orang-orang demi konsumerisme dan kesenangan di tempat yang jauh.
Membangun monokultur yang merusak keanekaragaman hayati dan bertanggung jawab atas pemiskinan tanah dicapai melalui deforestasi besar-besaran. Di Karibia, efeknya masih terasa sampai hari ini. Dalam esainya, dekolonial ekologi , Malcom Ferdinand, seorang peneliti di pusat penelitian nasional Prancis CNRS, menjelaskan bahwa perkebunanos memungkinkan kita untuk mengontekstualisasikan dan membuat sejarah Anthropocene dan capitalocene sehingga "genosida penduduk asli Amerika, perbudakan orang Afrika dan perlawanan mereka termasuk dalam sejarah geologi Bumi."
Ditandai oleh "patahan ganda, kolonial dan lingkungan," era modern menciptakan "cara hidup kolonial" dan "Bumi tanpa manusia," kata Malcom Ferdinand. Di satu sisi, ada populasi yang dominan, yaitu dari Barat. Di sisi lain, ada populasi yang didominasi, dianggap terlalu banyak dan dapat dieksploitasi.
Pemisahan antara "zona keberadaan" dan "zona ketidakberadaan" ini tetap ada sampai sekarang melalui ekonomi global ekstraksi, monokultur intensif, dan ekosida, yang mengarah pada ketidakadilan spasial: Kami mengeksploitasi tanah dan rakyat demi kepentingan konsumerisme dan kesenangan di suatu tempat yang jauh.
Bagi Ferdinand, wajah lain perkebunan adalah "politik penahanan" - rujukan ke kapal-kapal budak - di mana minoritas menyedot energi vital dari mayoritas dan mendapat untung secara material, sosial dan politik dari "Negro," seorang manusia direduksi menjadi alat untuk mengerjakan tanah.
"Sejak tahun 1970-an," kata Ferdinand kepada Le Monde , "peneliti Afrika-Amerika telah mencatat bahwa limbah beracun telah dibuang di dekat daerah yang dihuni oleh komunitas kulit hitam. Mereka telah menyebut praktik ini untuk mengekspos minoritas ras terhadap bahaya lingkungan 'rasisme lingkungan.'"
Contohnya adalah rangkaian tanaman industri antara Baton Rouge dan New Orleans (Louisiana), dijuluki Cancer Alley, yang merupakan rumah bagi populasi kulit hitam yang menetap di sana setelah perbudakan dan pemisahan dan memiliki tingkat kanker yang kadang-kadang 60 kali lebih besar daripada rata-rata nasional.
Cancer Alley pada tahun 1972 - Sumber: Arsip Nasional di College Park
Ferdinand juga menunjukkan bahwa di Perancis, uji coba nuklir tidak dilakukan di tanah Prancis tetapi di Aljazair dan Polinesia. Peneliti juga menyoroti bagaimana Martinique dan Guadeloupe telah terkontaminasi oleh penggunaan pestisida beracun Chlordecone dalam produksi pisang, mengatakan bahwa itu adalah bab lain dalam sejarah "proses pertanian yang dipimpin oleh sejumlah kecil individu dari komunitas Creole turun. dari kolonis pemilik budak pertama di Antilles Prancis, "
"Pendekatan dekolonial memungkinkan kita untuk bergerak melampaui fraktur ganda, kolonial dan lingkungan. Ia berupaya menciptakan dunia yang lebih egaliter, lebih adil, dan untuk melakukan itu kita harus mempertimbangkan kembali hal-hal yang telah dibungkam," jelas Ferdinand.
Itulah salah satu prinsip dasar ekologi dekolonial: menempatkan nilai pada cara-cara yang berbeda, seringkali leluhur, untuk mendiami dunia, yang telah dirusak oleh penjajahan, diidealkan atau diubah menjadi cerita rakyat.
Di Amerika Latin, tempat teori dekolonial saat ini lahir, para pemikir seperti ekonom Ekuador Alberto Acosta Espinosa menyerukan hubungan baru dengan Bumi dan dengan orang lain. Mereka menyebutnya "buen vivir" (hidup dengan baik), dan itu terinspirasi oleh konsep Quechua tentang "berpikir dengan Bumi" yang juga dikembangkan oleh antropolog Amerika-Kolombia Arturo Escobar. Ini mempertanyakan pandangan dunia Barat - yang memisahkan alam dan budaya, tubuh dan roh, emosi dan akal - dan mengubah yang universal menjadi "jamur," versi universalitas yang mengakomodasi perbedaan.
Cara-cara baru untuk menghuni dunia ini juga mencontohkan diri mereka pada "kosmologi diplomatik," kata peneliti Bolivia Diego Landivar, merujuk pada konstitusi Bolivia yang diajukan oleh mantan presiden Evo Morales, yang mengakui Pachamama (Ibu Pertiwi) sebagai subjek hukum. Ekuador juga menjadikan alam sebagai subjek hukum, dan Sungai Vilcabamba memenangkan kasus terhadap kotamadya Loja, yang dituduh menyimpan sejumlah besar batu dan bahan galian di sungai.
Ekologi dekolonial membentuk cakrawala baru yang non-ekstraktif: Ekologi pengunduran diri
Pemikiran dekolonial mengundang kita untuk menyatukan pengetahuan lokal dengan penelitian ilmiah dan teknologi. Ini juga merupakan rekomendasi dari laporan 2019 oleh Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim, yang menyerukan promosi agroekologi. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB setuju. Mempertimbangkan kepercayaan dan praktik asli terkadang berarti tidak mengeksploitasi sumber daya alam tertentu. Di Australia, misalnya, komunitas Aborigin mengakhiri pariwisata di Uluru (Ayers Rock), situs keramat yang menarik 300.000 pengunjung per tahun.
"Ekologi dekolonial membentuk cakrawala baru yang non-ekstraktif: Ekologi pengunduran diri," kata Diego Landivar. "Dalam pandangan dunia Barat, jika kita dapat memikirkan sesuatu, kita dapat melakukannya. Hari ini, kita bahkan berpikir tentang menjajah Mars. Tetapi saya tidak percaya kita dapat menjajah bulan, langit, Mars, hanya karena mereka kosong ."
Coumba Sow, ahli agroekonomi di FAO, mengatakan bahwa pengetahuan tradisional setempat sering memungkinkan kita untuk lebih memahami fenomena alam dan menemukan solusi yang efektif. Dalam sebuah wawancara pada tahun 2019 dengan Le Monde Afrika , ia mengingat kembali pengalaman Yacouba Sawadogo, yang
"sejak 1980 telah menggunakan teknik pertanian leluhur, zaï, yang melibatkan pembuatan penghalang batu untuk menghentikan air mengalir, dan juga menggunakan saluran yang digali oleh rayap. untuk mengumpulkan air. Dengan cara ini, dia merebut kembali puluhan ribu hektar dari gurun Sahara."
Menurut Coumba Sow, "banyak penelitian menunjukkan bahwa petani lokal yang menggunakan praktik agroekologi tidak hanya lebih mampu melawan tetapi juga untuk mempersiapkan perubahan iklim, karena mereka tidak kehilangan hasil panen karena kekeringan ... Secara tradisional, manusia mengolah tanah sesuai dengan prinsip-prinsip ekologis yang sama yang dipromosikan agro-ekologi, prinsip-prinsip yang tertanam dalam praktik pertanian adat."
Kamis, 13 Februari 2020
Feminisme Anti-Imperialis Gerwani di Panggung Perang Dingin
13 February 2020 | Ruth Indiah Rahayu
Ilustrasi oleh Jonpey. Karya-karyanya dapat dijumpai di sini.
“Sedjak pagi2 pada 17 Djanuari 1962, Gedung PB Front
Nasional didatangi berdujun-dujun sukarelawan untuk melaksanakan komando
rakjat. Kami, wanita yang bergabung dalam Gerwani djuga tak ketinggalan siang
hari berdatangan memenuhi ruang dalam Gedung Front Nasional……. Wakil Gerwani
menjerahkan sedjumlah besar formulir pada Front Nasional dan menjatakan siap
sedia djuga untuk mendapatkan latihan2 jang diperlukan (….) (Api Kartini,
Januari 1962)
API KARTINI edisi Januari 1962 terbit penuh gelora.
Cuplikan kalimat di atas merupakan paragrap awal dari reportase bertajuk
“Pendaftaran Sukarelawan Untuk Membebaskan Irian Barat”. Reportase itu
menunjukkan sikap Gerwani dalam mendukung kebijakan Presiden Soekarno untuk
menanggapi serangan Belanda pada 15 Januari 1962 terhadap Angkatan laut RI.
Kaum perempuan diminta memberikan dorongan kepada suami,
anak, bahkan dirinya sendiri untuk menjadi sukarelawan pembebasan Irian Barat.
Sebagai catatan, dalam banyak bagian di tulisan ini saya tetap menggunakan istilah
Irian Barat sesuai masanya. Istilah “pembebasan”, sekalipun sangat problematis,
juga akan digunakan mengingat konteks zamannya serta sebagai nama resmi
kampanye pemerintahan Sukarno.
Saat itu Gerwani merupakan satu-satunya organisasi
perempuan yang memelopori mobilisasi sukarelawan untuk pembebasan Irian Barat.
Tindakan itu mendapat pujian dari Ibu Hurustiati (isteri Soebandrio, Wakil
Pedana Menteri) yang saat itu menjadi Ketua Kongres Wanita Indonesia (KOWANI).
Dilihat dari situasi hari ini, mobilisasi sukarelawan
untuk pembebasan Irian Barat tentu dapat mengundang kegusaran banyak pihak. Di
satu sisi, kita memiliki kebiasaan berpikir yang anakronistis, yaitu
menganalisasi peristiwa tidak seturut konteks waktu-ruang pada masanya dalam
membaca sejarah. Di sisi lain, kasus pelanggaran HAM di Papua, termasuk konflik
dan kerusuhan, penangkapan aktivis Papua dan pembela Papua adalah fakta-fakta
keras yang tidak bisa diabaikan.
Adalah relevan untuk dipertanyakan untuk apa waktu itu
pemerintah Indonesia menggelar operasi militer di Irian Barat, jika dalam
perjalanannya sumber daya alam dan manusia Papua hanya dieksploitasi, dibiarkan
marginal dalam proses transisi modernitas. Namun, tulisan ini tidak bermaksud
menganalisis proyek politik pembebasan Irian Barat dan warisan bom waktunya
pada Papua hari ini. Tulisan ini bermaksud untuk menelisik basis
argumentasi mengapa Gerwani cukup aktif dalam mobilisasi sukarelawan untuk Irian
Barat dan gerakan solidaritas anti-imperialisme lainnya.
Gerakan Era Perang
Dingin
Barangkali kita sudah mulai lupa terhadap era Perang
Dingin yang pernah terjadi dalam sejarah dunia sebagai kontestasi kekuatan
militer, ekonomi-politik, dan teknologi antara blok “Barat” yang disebut
“kapitalis” dan dipimpin oleh AS versus blok “Timur” yang disebut “sosialis”
dan dipimpin oleh Uni Soviet. Perang Dingin dimulai setelah periode fasisme
Nazi Jerman dan Jepang berakhir, hingga tersisa dua blok besar tersebut beserta
kroni-kroninya.
Pada 1947 Presiden AS Harry S. Truman mencetuskan sebuah
doktrin (yang kelak dikenal sebagai “Doktrin Truman”) untuk mengendalikan
ekspansi Uni Soviet (komunisme internasional). Salah satu bunyi doktrin
tersebut adalah “mendukung masyarakat dunia yang bebas” berdasarkan asumsi
bahwa politik komunisme internasional yang digaungkan Uni Soviet bersifat
totaliter dan memberangus kebebasan. Saat itu Doktrin Truman diwujudkan secara
internasional dengan membantu Yunani dan Turki agar tidak terjatuh ke dalam
hegemoni Uni Soviet.
Perang Dingin memang bukan perang terbuka. Perang itu
dilakukan atas nama solidaritas membantu negara lain yang sedang berada dalam
ancaman AS maupun Uni Soviet. Menurut Prasenjit Duara,[1] tatanan Perang Dingin
muncul dari rekonfigurasi ulang sejarah panjang imperialisme dan nasionalisme
selama abad ke-19 hingga 20.
Persaingan Perang Dingin memberikan kerangka rujukan di
mana hubungan baru antara imperialisme dan nasionalisme berusaha mengakomodasi
perkembangan dekolonisasi dan revolusi hak-hak global. Namun, pada gilirannya,
akomodasi ini menghasilkan perkembangan multikulturalisme, militerisme, ideologi
baru, dan mode pembentukan identitas, sehingga menghasilkan sebuah konstelasi
atau konfigurasi.
Konfigurasi itu pun kemudian berkembang, berubah yang
dipengaruhi oleh faktor sejarah lainnya termasuk ras, jenis kelamin, kelas, dan
agama.
Hubungan antara imperialisme dan nasionalisme tidak
seluruhnya dalam kontradiksi ataupun interaksi. Malaysia dan Inggris berkembang
dalam interaksi imperialisme dan nasionalisme yang kepentingannya dapat
berjalan sejajar, sementara Indonesia dan Belanda dalam kontradiksi imperialisme
dan nasionalisme. Itu sebabnya dalam konteks dekolonisasi, wilayah-wilayah yang
diklaim “milik” Belanda harus direbut untuk menjadi milik nasional Indonesia.
Wilayah Irian Barat termasuk dalam sengketa sejak Konferensi Meja Bundar (KMB)
pada 1949.
Dimas Dwi Kurnia (2019) telah menulis “Peranan Gerwani
Dalam Pembebasan Irian Barat 1950-1963” dalam Jurnal Prodi Sejarah, Universitas
Negeri Yogyakarta, menjelaskan bahwa peristiwa pembebasan Irian Barat harus
ditarik ke masa Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949.
Dalam perjanjian KMB untuk pertama kalinya dibahas urusan
Irian Barat antara Indonesia dan Belanda. Kedua negara, mantan penjajah dan
jajahan, berbeda pendapat.
Menurut Indonesia, kedaulatan Indonesia meliputi tanah
bekas jajahan Belanda, yang sebelumnya disebut Hindia Belanda, hingga termasuk
Irian Barat. Sementara Belanda memperlakukan Irian Barat bukan sebagai Hindia
Belanda dan karena itu menolak menyerahkannya kepada Indonesia. Perbedaan
pendapat itu selanjutnya mewariskan masalah berkepanjangan di masa depan.
Pelbagai upaya dilakukan Indonesia, termasuk membentuk
Komisi Gabungan untuk melakukan penyelidikan di Irian Barat dan diplomasi
internasional. Hingga pada 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Operasi Trikora
(Tri Komando Rakyat) di Yogyakarta. Politik Soekarno saat itu penuh gaung
anti-imperialisme. Ia menggalang organisasi-organisasi massa, termasuk Gerwani
untuk mendukung gerakannya.[2]
Politik
Internasional Anti-Imperialisme Gerwani
Selama dekade pasca-kemerdekaan sampai 1960-an, sikap
politik Gerwani dalam menderaskan gaung anti-imperialisme sangat militan. Sikap
politik ini didasarkan pada solidaritas nasional dan internasional untuk
menciptakan perdamaian. Yang dimaksud menciptakan perdamaian di sini adalah
ikut serta mengganyang imperialisme yang menciptakan penindasan dan
ketidakdamaian dalam sanubari rakyat tertindas di seluruh dunia, termasuk di dalam
negeri. Sikap anti-imperialisme seperti itu tidak tersurat dinyatakan oleh
organisasi perempuan lainnya, baik dalam kata dan maupun tindakan politik.
Dalam konteks solidaritas internasional
anti-imperialisme, Gerwani menjadi anggota Women International Federeration
Democratic (WIDF) yang didirikan di Paris pada 1945. Dalam masa perang dingin
1947-1991, ketika tegangan politik dan militer antara “dunia Barat” yang
dipimpin oleh AS versus “dunia sosialis” yang dipimpin oleh Uni Soviet
memuncak, federasi perempuan internasional ini cenderung memberikan solidaritas
kepada negara-negara sosialis dan bekas jajahan. Keikutsertaan Gerwani di
dalamnya memenuhi kriteria sebagai organisasi perempuan dari negara bekas
jajahan yang masih tetap memperjuangkan anti-imperialisme.
Sikap politik anti-imperialisme itu ditunjukkan dalam
pidato Umi Sardjono selaku Ketua Umum Gerwani pada Kongres Gerwani ke-3 pada
1962. Ia menegaskan program politik internasional Gerwani meliputi: (1)
Membangun Front Internasional Anti-imperialis, (2) Mengembangkan solidaritas
perempuan NEFO (New Emerging Forces), (3) Melawan revisionis dalam gerakan
perempuan internasional yang pasifis (menciptakan perdamaian tanpa membela
negara yang sedang perang melawan imperialis).[3]
Dalam pidatonya itu, Umi Sardjono menggambarkan situasi
imperialis dunia: AS melakukan agresi dan teror berdarah ke Amerika Latin,
Korea, Jepang, dan Vietnam Selatan. Di Vietnam Selatan, AS melakukan penyebaran
racun-racun di ladang tani dan menjadikan petani sebagai kelinci percobaan
nuklir di Korea Selatan, lalu mencampuri urusan dalam negeri Panama dan
Venezuela. Sebagai salah satu titik wilayah kontradiksi pokok dunia, di Asia
Tenggara telah berkobar perjuangan rakyat yang sengit melawan berbagai bentuk
imperialisme dan neokolonialisme.
Sebagai gerakan perempuan yang berkedudukan di Asia
Tenggara, Gerwani berkewajiban meningkatkan kegiatannya dalam memenangkan
revolusi-revolusi rakyat di Asia Tenggara. Selain itu Gerwani mendukung
perjuangan kaum perempuan di Kuba, Jepang, Korea, Laos, Kamboja, Vietnam
Selatan, yang dengan gigih pantang mundur melawan imperialisme AS.[4]
Pada 1963 Gerwani telah menyelenggarakan pertemuan
persahabatan dan mempopulerkan perjuangan heroik rakyat Kuba, Korea, dan
Vietnam ke daerah-daerah di Indonesia. Gerwani juga menyambut misi Front
Nasional untuk Pembebasan Vietnam Selatan yang dipimpin oleh Prof. Nguyen Thin
Binh di Indonesia.[5]
Namun, Gerwani menyayangkan sikap WIDF belakangan menjadi
revisionis, menghindari perjuangan anti-imperialis dan hanya menitikberatkan
pada perjuangan perempuan untuk perdamaian berdasarkan prinsip “damai untuk
damai”. Padahal, “tak mungkin perdamaian terjadi selama imperialisme ada,
membunuh pejuang-pejuang kemerdekaan, dan masih membuat perang di mana-mana”.
Imperialisme membuat perempuan menderita, maka perjuangan melawan imperialisme
adalah membebaskan perempuan dari penderitaan.[6]
Bagi Gerwani, pengaruh revisionisme yang menjangkiti
gerakan perempuan internasional telah merusak dan melemahkan gerakan emansipasi
revolusioner, dan karena itu harus dilawan dengan keras. Solidaritas
antar-rakyat yang berjuang melawan imperialisme hanya mungkin jika disertai
perjuangan melawan revisionisme dalam gerakan perempuan. Gerwani telah
mengadakan kunjungan ke Uni Soviet, Republik Rakyat Tiongkok, Bulgaria, Kuba,
Korea Utara, dan juga menerima kunjungan gerakan perempuan dari Uni Soviet,
Cekoslovakia dan Hongaria, untuk saling memperkuat dukungan kepada perjuangan
melawan imperialisme.[7]
Politik Nasional
Anti-Imperialis Gerwani
Api Kartini edisi No.20/1962 melaporkan bahwa Ibu
Sundari Surachman dan Ibu S. Hanafi menjadi delegasi Gerwani untuk mengikuti
Musyawarah Internasional Wanita untuk Pelucutan Senjata pada 23-26 April 1962
di Wina, Austria. Pertemuan itu membahas perjuangan untuk kemerdekaan nasional
dan pelucutan senjata imperialis. Indonesia, Vietnam, dan Laos merupakan negara
yang menjadi sorotan. Khusus mengenai Indonesia, peserta delegasi dari pelbagai
negara memberikan dukungan solidaritas melalui Gerwani untuk perjuangan
pembebasan Irian Barat.
Bahkan Ny. Gloria Gaston, delegasi WIDF dan anggota dari
Persatuan Wanita Australia, telah menulis dan dimuat dalam Australia
Tribune (lalu dikutip oleh Harian Rakyat dan dimuat dalam Api
Kartini, 1962) bertajuk “Irian Barat Masalah Jang Paling Penting”. Ny. Gaston
berkunjung ke Indonesia dalam rangka menghadiri Kongres Gerwani ke-4, 14-17
Desember 1961 di Jakarta. Selain itu Ny. Gaston mendapat kesempatan untuk
keliling desa di Pulau Jawa dan bertemu dengan banyak perempuan desa.
Menurutnya, pembebasan Irian Barat dari kolonialisme Belanda merupakan hal
besar dan penting bagi rakyat Indonesia. Oleh sebab itu Ny. Gaston memberikan
dukungan bagi perjuangan pembebasan Irian Barat.
Bagi Gerwani, dukungan untuk pembebasan Irian Barat
merupakan kelanjutan dari perjuangan kemerdekaan (nasionalisme) yang belum
tuntas. Revolusi nasional itu bahkan masih harus dilanjutkan dengan revolusi
sosial bagi kemerdekaan rakyat tertindas. Sikap politik anti-imperialisme dan
kerja-kerja bagi pelayanan perempuan (dan anak) maupun pencegahan perkawinan
muda, anti-poligami, memperjuangkan hak kesejahteraan buruh dan petani
perempuan berjalan paralel.
Kemiskinan perempuan terjadi dalam konteks kolonialisme
dan imperialisme, di mana ide-ide ini berkawin dengan pemasungan hak perempuan
dalam perkawinan (rumah tangga).
Jadi, Gerwani pada masa itu masih berpandangan bahwa
kolonialisme/ imperialisme eksis dalam wujud kekuasaan Belanda di Irian Barat.
Mengutip artikel di majalah Anthropological Quarterly dari AS, sebuah
artikel di Api Kartini menggambarkan bahwa:
Pembesar Belanda, antara lain mengusir suku Muju sebanyak
13.000 djiwa yang semula tinggal di pesisir Barat Daya, Irian Barat. Tjara
mengusirnya adalah kedjam tanpa perikemanusiaan, jaitu polisi pada waktu-waktu
tertentu menghantjurkan gubuk-gubuk bangsa Irian di tengah-tengah hutan. Lalu
ternak-ternak dibinasakan. Orang Irian dipaksa bekerdja sebagai budak belian, sedangkan
orang jang tidak mau menurut didjebloskan ke dalam pendjara. Tindakan itu
berakibat bahwa suku bangsa tersebut mati kelaparan….Djika diingat bawah dalam
praktek-praktek jang demikian itu ada banjak kaum wanita dan anak-anak
(….) (Api Kartini, No 2, Tahun IV, Februari 1962)
Dengan demikian agenda Gerwani untuk mobilisasi umum bagi
sukarelawan untuk pembebasan Irian Barat adalah bagian penyelesaian kontradiksi
era Perang Dingin dalam konteks nasional. Sesungguhnya Gerwani juga menggalang
kekuatan progresif di negeri Belanda agar menarik mundur pasukannya di Irian
Barat.
Kontradiksi Agenda
Feminis Perang Dingin
Selama masa Perang Dingin, agenda gerakan feminis dunia
terpola dalam dua karakter yang kontradiktif. Bagi gerakan feminis di dunia
“Barat” yang “liberal”, khususnya AS, era Perang Dingin atau pasca-Perang Dunia
II adalah masa ketika perempuan dikembalikan ke dalam rumah tangga.
Selama masa Perang
Dunia II, para laki-laki diwajibkan untuk berperang dan kaum perempuan
menggantikan pekerjaan yang mereka tinggalkan.
Setelah perang usai, laki-laki kembali ke pekerjaannya
dan perempuan kembali mengurus rumah tangga. Keadaan penuh domestikasi
perempuan itu telah ditulis oleh Betty Friedan dalam Feminine Mystique (1963).
Pada saat bersamaan, gerakan feminis dari belahan dunia yang blok “Timur”
sedang berjuang untuk nasionalisme dan anti-imperialisme, seperti halnya
Gerwani dan anggota WIDF lainnya.
Meskipun kemudian terjadi ledakan baru gerakan pembebasan
perempuan di AS untuk keadilan gender, melawan kekerasan seksual, rasisme dan
ketimpangan sosial sebagai akibat perubahan sosial di negara tersebut. Sebagian
dari aktivis gerakan pembebasan perempuan di AS ini disebut Gerakan Perempuan
Kiri Baru (sayang sekali di Indonesia, gerakan perempuan Kiri Baru ini mendapat
stigma “gerakan perempuan liberal yang membuka BH mereka!”).
Gerakan feminis Perang Dingin pada dasarnya merupakan
gerakan transnasional, sekalipun terjadi penafsiran yang berbeda-beda dalam
konteks nasional. Organisasi perempuan internasional, seperti WIDF yang
agendanya membangun solidaritas anti-imperialisme kontradiktif dengan agenda
International Council of Women (ICW) yang berdiri pada 1888 di Washington D.C.
Selama Perang Dingin, ICW memperjuangkan agenda-agenda
liberal seperti hak sipil perempuan. Organisasi ini mewakili agenda feminis AS
yang berbeda dengan feminis di negara-negara mantan jajahan maupun “blok
Timur”.
Walaupun terdapat kontradiksi antara agenda WIDF dan ICW
selama masa Perang Dingin, tetapi keduanya memberikan sumbangan yang cukup
besar dalam komisi peningkatan status perempuan di PBB hingga terselenggara
konferensi-konferensi perempuan sedunia pada 1975 di Meksiko, konferensi kedua
di Copenhagen pada 1980, dilanjutkan di Nairobi pada 1985, dan di Beijing pada
1995. Tentu saja Gerwani tidak dapat mengikuti konferensi perempuan
internasional yang diselenggarakan oleh PBB tersebut, sebab organisasi ini
telah menjadi korban Perang Dingin. Gerwani dibubarkan dan aktivisnya dipenjara
(dan tak sedikit yang dibunuh) dalam rangkaian paket Doktrin Truman untuk
menghancurkan gerakan-gerakan anti-imperialisme yang dikategorikan sebagai
bagian dari blok Soviet.
Namun, selalu terjadi kelahiran baru di tengah puing
penghancuran. Sejak 1980-an muncul banyak organisasi non-pemerintah yang
menangani pelbagai isu perempuan, yang sebagian dahulu dikerjakan oleh Gerwani.
Hanya saja, isu-isu yang ditangani organisasi perempuan saat ini minus gerakan
anti-imperialisme dan telah digantikan oleh gerakan anti-neoliberalisme yang
lebih “akademis” ketimbang gerakan massa dalam solidaritas internasional.
Mungkin karena itulah dalam konteks masalah Papua saat
ini, kita lebih banyak menyatakan persoalan pelanggaran HAM–meskipun memang
tepat—daripada meletakkan pada gerakan menolak neo-imperialisme yang menguasai
Papua dalam bentuk ekspansi industri ekstraktif.
Perang Dingin memang telah berlalu, tetapi
neo-imperialisme selalu memperbarui dirinya. Hari ini, kita memang perlu
kembali mengevaluasi kembali peran Gerwani dan kaum komunis dalam perebutan
Irian Barat (apakah mereka telah mengantisipasi dampak jangka panjang dari kampanye
tersebut? Bagaimana hubungan mereka dengan masyarakat asli Papua? dsb). Di luar
itu, kerja-kerja Gerwani dalam platform anti-imperialisme saat itu perlu
ditengok lagi oleh gerakan feminis hari ini.
***
[1] Prasenjit Duara, “The
Cold war as a Historical Period: An Interpretative Essay”, artikel ini diunduh
dari http://www.fas.nus.edu.sg/hist/doc/duara pada
5 Februari 2020
[2] Dimas Dwi Kurnia,
“Peranan Gerwani Dalam Pembebasan Irian Barat”, Jurnal Prodi Ilmu Sejarah,
Vol. 4, Nomor 1, Tahun 2019, Univesitas Negeri Yogyakarta
[3] Laporan Umi Sardjono,
Ketua Umum DPP Gerwani ke Sidang Pleno ke-3, 1964, hal 15-20
[4] Laporan Umi Sardjono,
hal 15
[5] Laporan Umi Sardjono,
hal 16
[6] Laporan Umi Sardjono,
hal 18
[7] Laporan Umi Sardjono,
hal 19
Tentara Jerman Boleh Tolak Perintah jika Berpotensi Langgar HAM
Oleh: Tony Firman - 13 Februari 2019
Kanselir Jerman Angela Merkel telah dilayani oleh tentara dari Jerman
di Angkatan Darat Jerman yang dipimpin oleh NATO di pangkalan militer Rukla
sekitar 100 km (62,12 mil) barat ibukota Vilnius, Lithuania. AP Photo /
Mindaugas Kulbis
Personel Bundeswehr dibolehkan menolak perintah atasan
jika dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.
Sejak Adolf Hitler mengambil alih kekuasaan pada 1933, Jerman
perlahan diubah menjadi negara polisi. Semuanya diatur ketat dalam garis besar
haluan partai Nazi yang bercorak fasis-militeristik.
Sejak 1934, Hitler tidak hanya menjabat kanselir, tapi
juga presiden. Dua jabatan itu bersifat absolut di tangannya sebagai pemimpin
tertinggi dan tunggal (Führer) yang tengah membangun Jerman Raya yang bebas
dari pengaruh Yahudi dan Komunis.
Hitler paham betul ambisinya mustahil tercapai tanpa militer, paramiliter, polisi dan intelijen dengan otoritas yang besar. Karena itulah Nazi mengkoordinasikan ulang angkatan bersenjata ke dalam tubuh Wehrmacht, mendirikan organisasi paramiliter seperti Schutzstaffel (SS) dan Sturmabteilung (SA), serta polisi rahasia Gestapo.
Hitler paham betul ambisinya mustahil tercapai tanpa militer, paramiliter, polisi dan intelijen dengan otoritas yang besar. Karena itulah Nazi mengkoordinasikan ulang angkatan bersenjata ke dalam tubuh Wehrmacht, mendirikan organisasi paramiliter seperti Schutzstaffel (SS) dan Sturmabteilung (SA), serta polisi rahasia Gestapo.
Pada 2 Agustus 1934, Hitler lantas mengubah isi
sumpah jabatan pengangkatan personel Angkatan Darat. Loyalitas personel yang
awalnya terarah ke Republik, bendera, dan konstitusi kini berpindah ke Hitler
sang Führer.
Perhatikan isi sumpah jabatan militer Wehrmacht: "Aku bersumpah demi Tuhan Yang Mahakuasa, sumpah suci ini: Aku akan memberikan kepatuhan tanpa syarat kepada Führer Reich Jerman, Adolf Hitler, Panglima Tertinggi Wehrmacht, dan sebagai prajurit pemberani, aku akan siap kapan pun juga untuk mempertaruhkan hidupku demi sumpah ini.
Mulanya, sebelum diubah Hitler, sumpah jabatan prajurit berbunyi: "Aku bersumpah demi Tuhan Yang Mahakuasa, sumpah suci ini: Aku akan selalu setia dan jujur melayani rakyat dan negaraku dan sebagai prajurit pemberani aku akan akan siap kapan pun juga untuk mempertaruhkan hidupku demi sumpah ini."
Seorang tentara Jerman era Nazi dihadapkan pada beban berat. Ia wajib mematuhi perintah atasan, termasuk perintah untuk menghabisi warga sipil yang tidak berdaya. Jika gagal melaksanakan tugas, ia akan harus siap dihukum, bahkan dieksekusi mati. Pilihannya praktis hanya dua: siap-siap jadi kejam tanpa ampun atau dibunuh.
Namun, sekalipun aturannya keras, tak sedikit tentara yang membangkang. Buku Military Psychology: Concepts, Trends and Interventions (2016) yang disunting oleh Nidhi Maheshwari dan Vineeth V. Kumar menyebutkan angkatan bersenjata Jerman mengeksekusi sekitar 15.000 prajurit yang dianggap membelot atau tak mematuhi perintah atasan. Sebanyak 50.000 lainnya bahkan dieksekusi karena melakukan kesalahan kecil. Tentu tak semua pembangkang dieksekusi. Sebagian harus membayarnya dengan kemalangan hidup.
Sejarawan Northern Arizona University David H. Kitterman menemukan 153 tentara Jerman yang menolak perintah untuk mengeksekusi orang Yahudi, sandera, kaum partisan (pejuang antifasis), atau tahanan perang.
Letnan Satu (Lettu) Klaus Hornig adalah salah satunya. Menurut buku Perpetrators: The World of the Holocaust Killers (2017) karya Günter Lewy, Hornig berdinas di Batalyon Polisi 306. Pada 1941, ia dikirim ke Lublin, Polandia, yang saat itu diduduki Nazi. Di sana, ia diperintahkan untuk menembak 780 tahanan perang, termasuk orang Yahudi. Nurani Hornig bergejolak. Ia memutuskan menolak perintah. Alasannya, perintah itu melanggar Pasal 42 dalam Kode Etik Militer Jerman.
Akhirnya Hornig ditarik dari Lublin dan dikirim ke Frankfurt, Jerman. Di sana ia dijatuhi hukuman dengan dakwaan "merusak moral institusi". Sejak itu, hidupnya berpindah-pindah dari penjara ke penjara. Ia sempat dijebloskan ke kamp konsentrasi Yahudi. Tragisnya, setelah Nazi kalah perang, Hornig sempat dicurigai oleh para tahanan kamp sebagai mata-mata tentara Jerman.
Sebenarnya, Pasal 42 yang menjelaskan tentang batasan
seorang prajurit yang dapat menolak perintah alasan dengan alasan-alasan
tertentu sudah ada dalam KUHP Militer Jerman sejak 1872.
Dikutip dari buku Robert B. Kane berjudul Disobedience and Conspiracy in the German Army, 1918–1945 (2002), Pasal 42 berbunyi: "Jika perintah eksekusi yang diberikan sesuai tugas melanggar undang-undang hukum pidana, atasan yang memberikan perintah itu sendiri yang bertanggung jawab.
Dikutip dari buku Robert B. Kane berjudul Disobedience and Conspiracy in the German Army, 1918–1945 (2002), Pasal 42 berbunyi: "Jika perintah eksekusi yang diberikan sesuai tugas melanggar undang-undang hukum pidana, atasan yang memberikan perintah itu sendiri yang bertanggung jawab.
Namun, bawahan yang mematuhi perintah dapat dihukum atas
tuduhan sebagai kaki tangan jika ... dia tahu bahwa perintah tersebut
melibatkan suatu tindakan yang merupakan kejahatan atau pelanggaran sipil dan
militer."
Namun, sejak naiknya Hitler menjadi orang nomor satu di Jerman, aturan tersebut diterabas. Beberapa pasal dalam Hukum Pidana Militer lainnya juga diubah guna menyesuaikan program Nazi meski dalam kasus Pasal 42, sangat sedikit yang diubah.
Pasal tersebut dilanggar tiap kali terjadi perang besar. Misalnya saat Perang Dunia I.
Gary Sheffield, profesor dari University of Birmingham yang meneliti topik-topik kejahatan perang, menyebutkan bahwa selama Perang Dunia I Jerman mengeksekusi 48 prajurit yang dianggap membangkang. Negara-negara lain yang terlibat dalam perang tersebut pun melakukan hal yang sama.
Dalam pelatihan dasar militer memang terdapat doktrin tentang kewajiban menjalankan perintah atasan tanpa syarat. Namun, pada titik inilah Jerman pasca-Perang Dunia II mengambil jalan yang berbeda.
Namun, sejak naiknya Hitler menjadi orang nomor satu di Jerman, aturan tersebut diterabas. Beberapa pasal dalam Hukum Pidana Militer lainnya juga diubah guna menyesuaikan program Nazi meski dalam kasus Pasal 42, sangat sedikit yang diubah.
Pasal tersebut dilanggar tiap kali terjadi perang besar. Misalnya saat Perang Dunia I.
Gary Sheffield, profesor dari University of Birmingham yang meneliti topik-topik kejahatan perang, menyebutkan bahwa selama Perang Dunia I Jerman mengeksekusi 48 prajurit yang dianggap membangkang. Negara-negara lain yang terlibat dalam perang tersebut pun melakukan hal yang sama.
Dalam pelatihan dasar militer memang terdapat doktrin tentang kewajiban menjalankan perintah atasan tanpa syarat. Namun, pada titik inilah Jerman pasca-Perang Dunia II mengambil jalan yang berbeda.
Humanis Pasca-Nazi
Setelah keok pada Perang Dunia II, Jerman melakukan
proses
denazifikasi untuk melenyapkan sisa-sisa kebudayaan
fasis yang melekat pada seluruh aspek kehidupan sosial.
Proses denazifikasi, angkatan bersenjata Jerman beserta
paramiliternya dibubarkan. Segala peralatan tempur yang dipanggul Wehrmacht
dilucuti. Jerman Barat butuh waktu sampai satu dekade untuk membentuk angkatan
bersenjata baru bernama Bundeswehr pada 1955.
Salah satu tantangan berat Bundeswehr adalah memastikan tentara tidak akan menjadi “negara di dalam negara” seperti yang sudah terjadi di era sebelumnya. Tak heran, di beberapa kota, orang yang memakai atribut atau seragam militer di beberapa kota malah mengundang tatapan aneh. Beberapa bahkan dihadiahi bogem mentah dari penduduk setempat.
Pasca-Perang Dunia II, masyarakat Jerman (khususnya Jerman Barat) memang tak begitu ramah terhadap hal-hal yang berbau militer.
Pembaruan dalam tubuh Bundeswehr juga masih terasa hari ini, misalnya dalam pengurangan personel dari yang mulanya 250.000 pada 2010, menjadi 185.000 tujuh tahun kemudian. Lagi-lagi, para prajurit Bundeswehr juga berhak menolak perintah atasan apabila dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Dasar penolakannya termaktub dalam Peraturan 154 tentang Kepatuhan pada Perintah Tertinggi sebagaimana tertera dalam buku panduan militer Jerman (1992).
Di situ tertulis bahwa tentara Jerman bisa menolak perintah atasan jika: 1) merendahkan martabat manusia dari pihak ketiga atau penerima perintah; 2) tidak ada gunanya bagi kesatuan; 3) dalam situasi tertentu di mana prajurit tidak bisa dengan layak menjalankan perintah atasan.
Yang lebih tegas lagi: tentara Jerman “dilarang mematuhi perintah jika perintah itu dapat menyebabkan kejahatan.”
Prajurit yang menolak perintah atasan dengan kondisi-kondisi di atas tak dapat dikenai hukuman. Perintah bahkan bisa ditolak dalam situasi pertempuran langsung sekalipun.
Salah satu tantangan berat Bundeswehr adalah memastikan tentara tidak akan menjadi “negara di dalam negara” seperti yang sudah terjadi di era sebelumnya. Tak heran, di beberapa kota, orang yang memakai atribut atau seragam militer di beberapa kota malah mengundang tatapan aneh. Beberapa bahkan dihadiahi bogem mentah dari penduduk setempat.
Pasca-Perang Dunia II, masyarakat Jerman (khususnya Jerman Barat) memang tak begitu ramah terhadap hal-hal yang berbau militer.
Pembaruan dalam tubuh Bundeswehr juga masih terasa hari ini, misalnya dalam pengurangan personel dari yang mulanya 250.000 pada 2010, menjadi 185.000 tujuh tahun kemudian. Lagi-lagi, para prajurit Bundeswehr juga berhak menolak perintah atasan apabila dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Dasar penolakannya termaktub dalam Peraturan 154 tentang Kepatuhan pada Perintah Tertinggi sebagaimana tertera dalam buku panduan militer Jerman (1992).
Di situ tertulis bahwa tentara Jerman bisa menolak perintah atasan jika: 1) merendahkan martabat manusia dari pihak ketiga atau penerima perintah; 2) tidak ada gunanya bagi kesatuan; 3) dalam situasi tertentu di mana prajurit tidak bisa dengan layak menjalankan perintah atasan.
Yang lebih tegas lagi: tentara Jerman “dilarang mematuhi perintah jika perintah itu dapat menyebabkan kejahatan.”
Prajurit yang menolak perintah atasan dengan kondisi-kondisi di atas tak dapat dikenai hukuman. Perintah bahkan bisa ditolak dalam situasi pertempuran langsung sekalipun.
Pada 2007 batasan penolakan perintah kembali dirumuskan
oleh Majelis Rendah Parlemen (Bundestag). Dalam diskusi tersebut disebutkan
bahwa prajurit Angkatan Bersenjata Federal Jerman wajib melaksanakan perintah
dengan sungguh-sungguh. Menolak perintah atasan juga tidak dibenarkan jika
hanya karena perbedaan pandangan pribadi. Di sisi lain, kewajiban itu tak
menuntut kepatuhan tanpa syarat. Prajurit tetap diberi ruang untuk memikirkan
konsekuensi perintah atasan.
Hukum militer Jerman mengajarkan bagaimana seorang prajurit diajak berpikir terlebih dahulu ketika menerima perintah dari atasan, alih-alih sekadar menjalankannya.
Hukum militer Jerman mengajarkan bagaimana seorang prajurit diajak berpikir terlebih dahulu ketika menerima perintah dari atasan, alih-alih sekadar menjalankannya.
Bukan artinya Bundeswehr bebas dari masalah. Beberapa
kasus telah merusak reputasinya. Pada 2004 lalu, misalnya, media memberitakan
perploncoan dengan penyiksaan terhadap calon prajurit. Penyiksaan
dilakukan dengan menyiram air ke kepala calon prajurit yang sudah dibungkus
dengan kain dan dalam keadaan tubuh terikat. Ada pula yang disetrum hingga
trauma.
Pada 2017 publik Jerman digegerkan dengan laporan Kementerian Pertahanan Jerman mengenai pelecehan seksual terhadap sejumlah personel baru perempuan. Prajurit perempuan ini disuruh menari erotis di sebuah kamar di barak. Saat mengikuti pembelajaran di kelas, mereka juga disuruh telanjang, payudara serta area genitalnya digerayangi dan difoto. Para pelaku kemudian dimutasi.
Di luar kasus-kasus di atas yang lazim terjadi di banyak institusi militer di berbagai dunia, kebrutalan rezim Nazi tampaknya telah mendorong Jerman untuk memberi ruang bagi tentara agar berpikir masak-masak ketika mendapat perintah dari atasan.
Penulis: Tony Firman
Editor: Windu Jusuf
Pada 2017 publik Jerman digegerkan dengan laporan Kementerian Pertahanan Jerman mengenai pelecehan seksual terhadap sejumlah personel baru perempuan. Prajurit perempuan ini disuruh menari erotis di sebuah kamar di barak. Saat mengikuti pembelajaran di kelas, mereka juga disuruh telanjang, payudara serta area genitalnya digerayangi dan difoto. Para pelaku kemudian dimutasi.
Di luar kasus-kasus di atas yang lazim terjadi di banyak institusi militer di berbagai dunia, kebrutalan rezim Nazi tampaknya telah mendorong Jerman untuk memberi ruang bagi tentara agar berpikir masak-masak ketika mendapat perintah dari atasan.
Penulis: Tony Firman
Editor: Windu Jusuf
Kebrutalan rezim Nazi telah mendorong tentara Jerman untuk berpikir
masak-masak ketika mendapat perintah dari atasan.
Langganan:
Postingan (Atom)