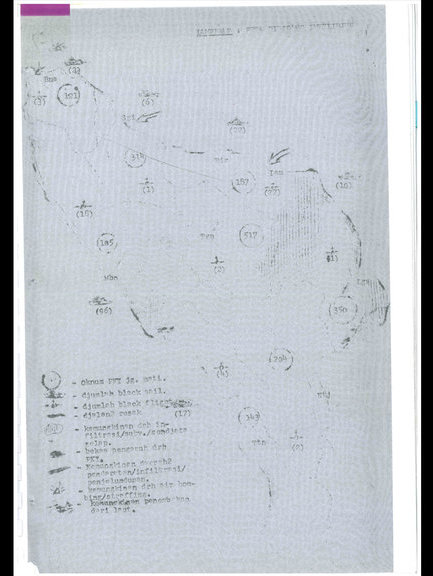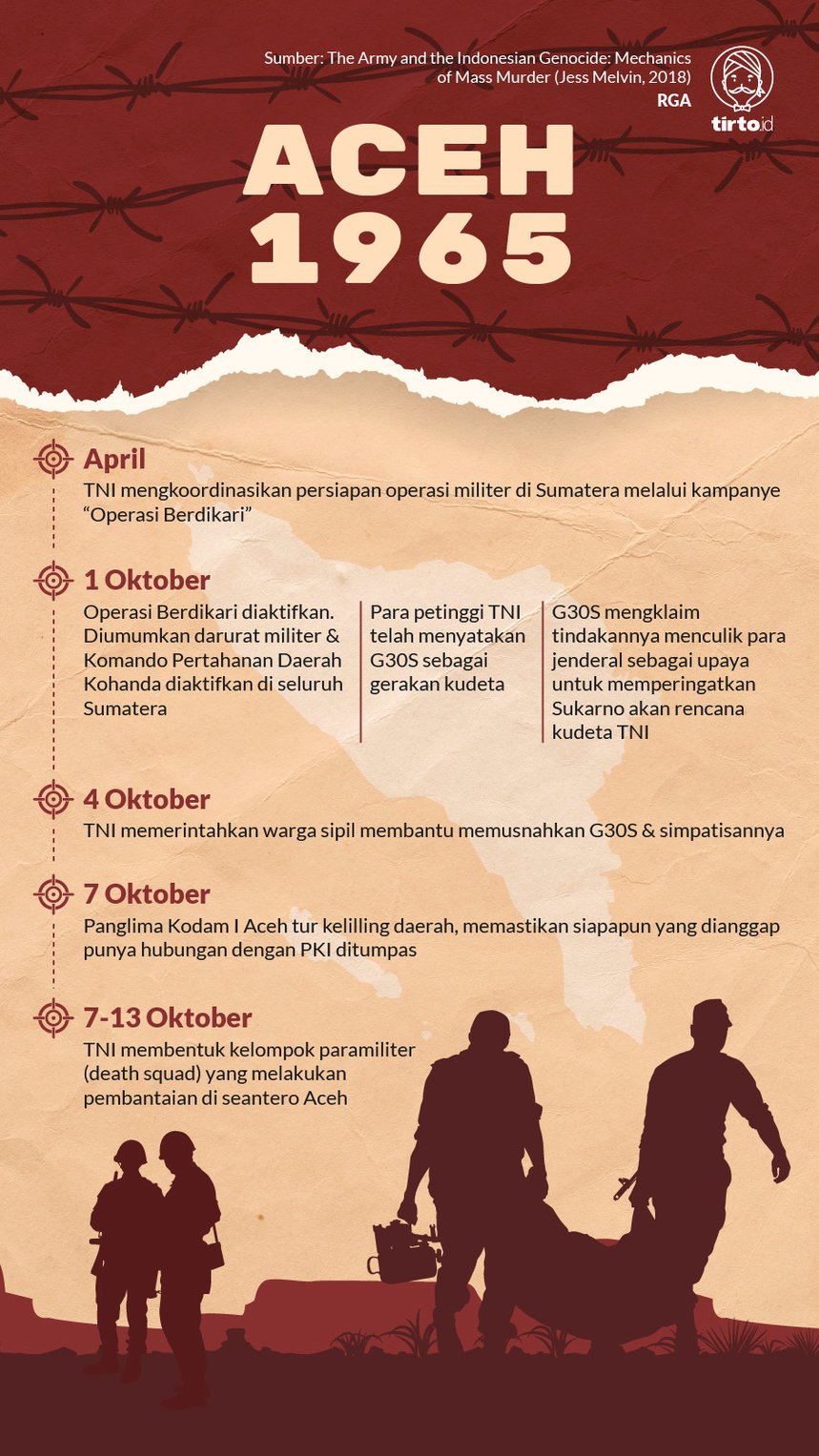Selasa 02 Okt 2018 05:01 WIB
Red: Muhammad Subarkah
Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Foto: gahetna.n
pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948,
bukanlah membela diri seperti dikatakan Aidit
Oleh: Andy Ryansyah, Pegiat
Jejak Islam untuk Bangsa (JIB)
Seorang antropolog Amerika, Robert Jay, yang mulai tahun
1953, turun ke Jawa Tengah menggambarkan kekejaman PKI. “Mereka menggunakan
kekuatan mereka untuk melenyapkan bukan saja para pejabat pemerintah pusat,
tapi juga penduduk biasa yang merasa dendam.
Mereka itu terutama ulama-ulama tradisionalis, santri dan
lain-lain yang dikenal karena kesalihan mereka kepada Islam. Mereka ini
ditembak, dibakar sampai mati, atau dicincang-cincang, kadang-kadang
ketiga-tiganya sekaligus. Masjid dan madrasah dibakar, rumah-rumah pemeluknya dirampok
dan dirusak.”
Seorang narasumbernya bercerita kepada Robert Jay,
“Soalnya begini Mas. Kami mulai mendengar kabar itu dari Madiun. Ulama-ulama
dan santri-santri mereka dikunci di dalam madrasah, lalu madrasah-madrasah itu
dibakar. Mereka itu tidak berbuat apa-apa, orang-orang tua yang sudah ubanan,
orang-orang dan anak-anak laki-laki yang baik. Hanya karena mereka itu muslim
saja. Orang dibawa ke alun-alun kota, di depan masjid, kemudian kepala mereka
dipancung. Parit-parit di sepanjang jalan itu digenangi darah setinggi tiga
sentimeter, Mas.”
Di Madiun, Sin Po menulis laporan dari saksi mata.
Sesudah perebutan kekuasaan menyusul tindakan pembersihan,
“Semoea pemimpin Masjoemi dan PNI ditangkep atawa
diboenoeh dengan tida dipreksa poela. Kekedjaman di Kota Madiun djadi memoentjak,
koetika barisan ‘warok’ ponorogo masoek kota dengen bersendjata revolver dan
klewang. Di mana ada terdapat orang-orang Masjoemi, PNI atawa jang
ditjoerigakan, zonder banjak tjingtjong lagi lantas ditembak. Belon poeas
dengan ini tjara, korban itoe laloe disamperi dan klwangnja dikasi bekerdja
oentoek pisahken kepalanja sang korban dari toeboehnja.
Kedjadian atawa pemboenoehan stjara ini dilakoekan di
berbagai bagian dari kota dan sakiternja, hingga dalam tempo beberapa hari
sadja darah manoesia telah membandjiri kota Madioen. Soenggoe keadahan sangat
mengerihkan teroetama djika orang melihat dengen mata sendiri, orang-orang jang
diboenoeh pating gletak di sepandjang djalan sampe bebrapa hari tida ada jang
mengangkat.”
Sin Po 1 Oktober 1948, memberitakan, ” pembrontakan
communist itoe ditoedjoekan kerna kaoem FDR-PKI merasa tida soeka pada Masjoemi
dan banjak sekali orang-orang jang Masjoemi di daerah jang didoedoekin oleh
communist telah diboenoe dengen kekedjaman.”
Di Madiun, Sin Po menulis laporan dari saksi mata.
Sesudah perebutan kekuasaan menyusul tindakan pembersihan,
Serangan ke Pesantren Sabilul Muttaqien
Belakangan tim koran Jawa Pos yang terdiri atas Maksum,
Sunyoto, dan Zainuddin, mewawancarai saksi-saksi hidup, baik tokoh-tokoh yang
turut dalam operasi penumpasan, maupun para korban yang luput dari aksi
pembantaian oleh kaum komunis. Hasil wawancaranya mengungkap PKI memakan
korban, khususnya kiai. Salah satu yang menjadi sasaran adalah Pesantren
Sabilul Muttaqien atau yang lebih dikenal dengan Pesantren Takeran.
Bersamaan dengan kudeta terhadap pemerintah, pendukung
PKI mengincar tokoh-tokoh dari Pesantren Takeran yang dianggap sebagai musuh
utama mereka. Sebab, Pesantren Takeran pimpinan Kiai Imam Mursjid Muttaqien
yang masih berusia 28 tahun itu adalah pesantren yang paling berwibawa di
kawasan Magetan..
Massa PKI ditangkap
di Madiun 1948.
Pada tanggal 17 September 1948, tepatnya hari Jumat Pon,
Kiai Hamzah dan Kiai Nurun yang berasal dari Tulungagung dan Tegal Rejo
berpamitan kepada Kiai Imam Mursjid. Kepergian Kiai Hamzah dan Kiai Nurun ke
Burikan itu ternyata untuk yang terakhir kalinya. Sebab pada hari Sabtu Wage,
18 September 1948, Pesantren Burikan diserbu oleh PKI, dan tokoh-tokoh
pesantren serta para santri, termasuk Kiai Hamzah dan Kiai Nurun yang masih ada
di pesantren tersebut, diseret ke Desa Batokan yang letaknya hanya 500 meter dari
Pesantren Burikan. Kiai Hamzah dan Kiai Nurun termasuk diantara para korban
yang dibantai oleh PKI di lubang pembantaian Batokan.
Seusai shalat Jumat tanggal 17 September 1948, Kiai Imam
Mursjid didatangi oleh tokoh-tokoh PKI. Muhammad Kamil kenal dengan beberapa
orang di antara tokoh PK yang datang itu, seperti Suhud dan Ilyas alias Sipit.
“Sipit sebenarnya santri Mas Imam Mursjid. Tapi entah mengapa dia bisa menjadi
PKI,” ujar Kamil,salah seorang saksi mata.
Sipit sendiri, menurut Kamil, ketika itu dikenal sebagai
kepala Takeran yang kemana-mana selalu membawa senapan. Tetapi sejak jauh hari,
Kiai Imam Mursjid sudah mulai meragukan kesetiaan Sipit. Hal itu terungkap dari
pernyataan Kiai Imam Mursjid kepada Kamil tentang iktikad baik Sipit.
“Waktu itu
saya sudah mengatakan bahwa Sipit tak bisa dipercaya lagi, sebab Sipit sudah
tak sembahyang lagi,” ujar Kamil mengingat-ingat.
Waktu didatangi oleh tokoh-tokoh PKI, Kiai Imam Mursjid
diajak keluar dari mushalla kecil di sisi rumah Kamil. Menurut Kamil, Kiai Imam
Mursjid akan diajak bermusyawarah mengenai Republik Soviet Indonesia dengan
PKI-nya. Keberangkatan Kiai Imam Mursjid bersama orang-orang PKI itu tentu saja
merisaukan warga pesantren, sebab warga pesantren tak menduga bahwa Kiai Imam
Mursjid akan menurut begitu saja diajak berunding oleh PKI.
Kiai Zakaria, salah seorang saksi yang diwawancarai Tim
Jurnalis Islam Bersatu (JITU), yang saat kejadian masih jadi santri (13 tahun)
di pesantren Sabilil Muttaqin, bercerita,
“Salah satu pendiri pesantren Sabilil Muttaqin, Kiai imam
mursyid didatangi oleh Suhud. Suhud adalah seorang camat PKI. Mobilnya hitam.
Di sisinya, berdiri dua orang yang satu membawa standgun
dan satu lagi membawa karaben. Di hadapan santri-santri, Suhud membaca,
‘innallaha laa yughoyyiruma bi koumin hatta laa yughoyyiruma bin anfusihim’.
Jadi dia itu mau melakukan perubahan di Indonesia. Lalu Kiai Imam Mursyid
diculik olehnya. Kata Suhud, pak Kiai mau diajak berunding. Pak Kiai dibawa ke
sana (sambil menunjuk arah Gorang Gareng). Tapi sampai sekarang tidak ada
datanya dimana beliau disedani (dibunuh)”. [8]
Waktu itu para santri di Takeran berkumpul dengan
perasaan was-was terhadap rencana kepergian kiai mereka bersama PKI. Setelah
Suhud menenangkan suasana dngan dalilnya, di depan pendapa pesantren Kiai Imam
Mursjid dinaikkan ke mobil. Tetapi sebelum mobil berangkat, Imam Faham, saudara
sepupu Kiai Imam Mursjid sekaligus santri yang setia, meminta kepada PKI agar
diperkenankan ikut naik mobil mendampingi pemimpinnya. Permohonan Imam Faham itu
dikabulkan oleh PKI dan mereka pun meluncur keluar kawasan pesantren.
Iskan, salah seorang saksi mata, juga menyatakan bahwa
Pesantren Takeran sudah dikepung oleh ratusan orang PKI.
“Setelah Mas Imam Mursjid dibawa dengan mobil, saya
melihat orang-orang PKI sudah berdiri melingkari pesantren. Mereka rata-rata
berpakaian hitam dengan memakai ikat kepala merah dan bersenjata,” ujar Iskan
sambil menitikkan air mata mengenang gurunya yang sangat dipatuhi itu.
Menurut Iskan, sebelum itu pihak PKI memang sudah mengancam,
jika Kiai Imam Mursjid tak mau menyerah dan mendukung mereka, maka pesantren
akan dibumihanguskan. Mungkin, menurut Iskan, apabila Jumat itu Kiai Imam
Mursjid tak berhasil dibawa PKI, bisa dipastikan pesantren akan dibakar dan
dengan demikian korban akan sangat besar. Iskan menduga, Kiai Imam Mursjid mau
ikut PKI untuk menghindari terjadinya korban yang lebih besar di antara para
pengikutnya.
Pada hari Minggu Kliwon, 19 September 1948, kurir PKI
yang lain datang lagi menyampaikan pesan bahwa Kiai Imam Mursjid belum bisa
pulang. Malah mereka mengatakan perundingan tersebut membutuhkan kehadiran Kiai
Muhammad Noer, sepupu Kiai Imam Mursjid yang selama itu ikut memimpin Pesantren
Takeran.
“Waktu itu mereka mengatakan bahwa Mas Imam Nursjid baru bisa pulang
kalau Kiai Muhammad Noer datang menjemput,” kata Kamil.
Kiai Muhammad Noer, begitu mendengar pesan dari kurir
tersebut, diam-diam mendatangi markas PKI di Gorang Gareng, 6 kilometer di
sebelah barat Takeran. Tapi di tengah jalan, ia ditangkap PKI dan sempat
ditawan di sebuah tempat di Takeran. Kurir PKI berulang kali datang lagi ke
pesantren setelah Kiai Muhammad Noer dibawa ke Gorang Gareng. Dia mengatakan
bahwa Kiai Imam Mursjid dan Kiai Muhammad Noer baru bisa kembali setelah Ustadz
Muhammad Tarmudji, adik Kiai Imam Mursjid yang juga sebagai tokoh pemuda,
datang menjemput ke Gorang Gareng.
PKI mengatakan bahwa Kiai Imam Mursjid dan Kiai Muhammad
Noer baru bisa kembali setelah Ustadz Muhammad Tarmudji, adik Kiai Imam Mursjid
yang juga sebagai tokoh pemuda, datang menjemput ke Gorang Gareng.
Mendapat informasi seperti itu, Tarmudji secepatnya
menyelamatkan diri. Apalagi dia juga diberi tahu bahwa dialah yang mendapat
giliran dicari PKI. Meskipun tak menemukan Tarmudji, PKI terus menangkapi
tokoh-tokoh pesantren seperti Ustadz Ahmad Baidawy, Muhammad Maidjo, Rofi’i,
Tjiptomartono, Kadimin, Reksosiswojo, Husein, Hartono, dan Hadi Addaba’. Yang
terakhir ini adalah guru pesantren yang didatangkan dari Al-Azhar, Kairo
(Mesir). Saat itu, Pesantren Takeran memang sangat terkenal dan muridnya datang
dari berbagai daerah termasuk dari luar Jawa.
Mereka itu akhirnya memang tak pernah kembali. Bahkan
sebagian besar ditemukan sudah menjadi mayat di lubang-lubang pembantaian PKI
yang tersebar di berbagai tempat di Magetan. Bahkan hingga tahun 1990, mayat
Kiai Imam Mursjid tak kunjung ditemukan. Dari daftar korban yang dibuat PKI
sendiri -daftar ini ditemukan oleh pasukan Siliwangi-, nama Kiai Imam Mursjid
tak ada.
Pembantaian di
sumur tua Cigrok
Di Desa Cigrok, sebelah selatan Takeran, terdapat sumur
tua yang digunakan PKI sebagai tempat pembuangan korban-korbannya. Sumur tua
Cigrok ini terletak di belakang rumah To Teruno, seorang warga yang sebenarnya
bukan orang PKI. Justru dialah yang melaporkan kegiatan PKI di sumurnya itu
kepada Kepala Desanya. Di dekat rumah To Teruno, tinggal pula Muslim, seorang
santri yang menjadi saksi kebiadaban PKI dalam melakukan pembantaian di sumur
tua itu tahun 1948.
Muslim menceritakan pada malam terjadinya penjagalan itu,
semua orang tak berani keluar rumah. Malam itu, dia mendengar suara bentakan
Surat, pimpinan PKI yang berasal dari Desa Petungredjo. Dia juga mendengar
suara orang menjerit histeris karena dianiaya. Muslim, yang diam-diam mengintip
melalui lubang dari rumahnya, melihat gerak-gerik orang-orang PKI itu dalam
keremangan malam. Muslim dapat mengenali salah satu korban yang mengumandangkan
adzan dari dalam sumur. Suara itu, menurutnya adalah suara K.H. Imam Sofwan
dari Pesantren Kebonsari.
Achmad Idris, tokoh Masyumi di Desa Cigrok yang ketika
itu sudah ditawan PKI, menyaksikan penjagalan biadab PKI dari kejauhan.
Meskipun sayup-sayup, dia sangat mengenal suara adzan K.H. Imam Sofwan yang
mengumandang dari dalam sumur itu, sebab Idris sering mendengarkan
pengajian-pengajian K.H. Imam Sofwan.
Menurut Idris, pembantaian oleh PKI di sumur Cigrok itu
tak dilakukan dengan senapan atau Klewang, akan tetapi dengan pentungan. Idris
mengungkapkan para tawanan dengan tangan terikat dihadapkan ke arah timur sumur
satu demi satu. Kemudian, seorang algojo PKI menghantamkan pentungan ke bagian
belakang tiap tawanan tersebut.
Waktu itu, Idris mengenang, ada tawanan yang segera
setelah dihantam langsung menjerit dan roboh ke dalam sumur. Tetapi ada pula
yang setelah dihantam, masih kuat merangkak sambil melolong-lolong kesakitan.
Tangan mereka menggapai-gapai mencari pegangan. Melihat para korban merangkak
seperti itu, orang-orang PKI kemudian menyeret begitu saja dan memasukkan
mereka hidup-hidup ke dalam sumur. K.H. Imam Sofwan, menurut Idris, termasuk
yang tak meninggal setelah dihantam.
Hal serupa juga dialami oleh kedua putra beliau, yakni
Kiai Zubair dan Kiai Bawani, yang dibantai di sumur tua Desa Kepuh Rejo, tak
jauh dari sumur Cigrok.
Orang-orang PKI yang melihat bahwa ternyata ada korban
yang masih hidup di dalam sumur, sama sekali tak peduli. Mereka lantas langsung
menimbuni sumur tersebut dengan jerami, batu, dan tanah. Karena itu, ada
pernyataan yang menyebutkan bahwa korban pemberontakan PKI tahun 1948
sebenarnya dikubur hidup-hidup. Muslim mengatakan, pada pagi hari seusai
pembantaian dia mendapati lanjaran (rambatan) kacang dan jerami di kebunnya
sudah habis.
“Rupanya orang-orang PKI membabat semua itu untuk menimbuni
sumur,” tutur Muslim yang diancam oleh PKI agar tutup mulut.
Yang dimasukkan ke lubang pembantaian Cigrok paling
sedikit berjumlah 22 orang. Di antara para korban itu, ada K.H. Imam Sofwan,
Hadi Addaba’ dan Imam Faham. Hadi Addaba’ sendiri adalah guru dari Mesir yang
ditugaskan mengajar di Pesantren Takeran. Sementara Imam Faham adalah santrinya
K.H. Imam Mursjid yang ikut mengiringi K.H. Imam Mursjid ketika dibawa mobil
PKI. Tetapi rupanya di tengah jalan kiai dan pengawalnya itu dipisah. Imam Faham
diturunkan di tengah jalan dan akhirnya ditemukan di dalam lubang pembantaian
Cigrok.
Kisah lainnya, pada hari Senin Legi, 20 September 1948,
tiba-tiba datang sebuah truk yang berisi orang-orang PKI baik laki-laki, maupun
perempuan. Seorang perempuan sekonyong-konyong berteriak keras kepada seluruh
penduduk Kauman. Dia mengatakan bahwa salah seorang anggota PKI telah mati
terbunuh di Kampung Kauman.
“Di atas truk memang ada mayat yang dibungkus kain dan
hanya kelihatan kakinya saja,” kata Parto Mandojo, yang ketika itu menjadi
pengusaha mebel makanan di Kauman.
Dia menceritakan bahwa perempuan yang berteriak tadi
menginginkan ada penduduk Kauman yang mengakui telah membunuh salah seorang
anggota PKI. Namun tak satu pun penduduk Kauman yang mengakuinya karena mereka
memang tak merasa pernah membunuh satu orang pun. Akhirnya rombongan PKI pergi
meninggalkan ancaman akan membumihanguskan Kampung Kauman. Ini adalah taktik
licik ‘mencari pembunuh’ ala PKI, karena sebenarnya, ingin menjebak lawan-lawan
yang akan menghalangi pemberontakan mereka.
Pada hari Jumat Kliwon, 24 September 1948, PKI seperti
kerumunan lebah yang menyerbu Kampung Kauman. Rumah-rumah dibakar sehingga
seluruh penghuni keluar dari persembunyiannya.
“Waktu itu seluruh warga laki-laki Kauman ditawan dan
digiring ke Masopati setelah tangan mereka ditelikung dan diikat dengan tali
bambu,” tutur Parto Mandojo.
Dalam aksi pembumihangusan Kampung Kauman itu, tak kurang
dari 72 rumah terbakar, dan sekitar 149 laki-laki digiring ke Maospati. Dari
Maospati seluruh tawanan dimasukkan ke dalam gudang pabrik rokok, kemudian
diangkut dengan lori milik pabrik gula ke kawasan Glodok.
“Dari glodok kami dipindahkan ke Geneng dan Keniten.
Tetapi sebelum disembelih, kami berhasil diselamatkan oleh tentara Siliwangi,”
ujar Parto Mandojo tentang peristiwa mencekam itu.
Suasana kota Madiun
yang rusak parah akibat pemberontakan PKI Madiun 1948.
Pembakaran Kampung Kauman pada dasarnya merupakan bagian
dari aksi PKI untuk memberangus pengaruh agama Islam di tengah masyarakat.
Sebab, sebelum aksi pembakaran itu, Madrasah Pesantren Takeran juga telah
dibakar, beberapa saat setelah Kiai Imam Mursjid tertawan. Pesantren Burikan
pun tak luput dari serbuan PKI. Kemudian para tokoh-tokoh pesantren seperti
Kiai Kenang, Kiai Malik, dan Muljono dibantai di Batokan. Korban lain dari
kalangan ulama yang dibantai oleh PKI adalah keluarga Pesantren Kebonsari,
Madiun.
Achmad Daenuri, putra K.H. Sulaiman Zuhdi Affandi dari
pesantren Mojopurno, menceritakan bahwa ayahnya adalah putra sulung Kiai
Kebonsari. Menurut Daenuri, ayahnya ditangkap oleh PKI, bersamaan dengan
ditangkapnya bupati Magetan. Sementara adik kandung ayahnya, K.H. Imam Sofwan
yang menjadi pimpinan Pesantren Kebonsari, ditangkap PKI bersama dengan dua
putranya yakni Kiai Zubair dan Kiai Bawani.
“Jadi setelah pemberontakan itu meletus,
pesantren-pesantren sudah benar-benar kehilangan pimpinan,” simpul Daenur.
Pak Kafrawi, saksi
penyerbuan PKI di Ponpes Gontor. Diwawancara bulan Agustus 2016 silam.sumber
foto:JITU
Di Pondok Pesantren Gontor, PKI juga menyebarkan
terornya, Seperti dituturkan oleh Kafrawi, saksi hidup yang diwawancarai Tim
Jurnalis Islam Bersatu (JITU), yang saat kejadian, masih jadi santri di
Pesantren Gontor, Ponorogo. Ketika itu pesantren Gontor dikuasai dan diancam
oleh PKI. Banyak orang PKI berpakaian hitam-hitam datang ke Gontor, lalu
mengancam.
“Kalau tidak mau menyerah, kita akan habiskan besok dan
akan kita duduki,” katanya.
Oleh kiai, Kafrawi dan anak-anak kecil lainnya disuruh
mengosongkan Gontor dan pindah ke timur Tulung Agung. Di Gontor hanya tersisa
ibu-ibu. Ia dan enam orang beserta anaknya yang masih kecil-kecil, lalu
berjalan menuju timur. Di perjalanan, mereka ketahuan PKI. Ditawanlah mereka.
“Akhirnya ditawan di tulung, anak gontor itu sekitar 50,
dan digiring lagi ke gontor setelah di pulung berapa minggu menjadi tawanan.
Pak Jahal (pengajar pesantren gontor) dan terutama yang senior dibawa ke
Ponogoro lebih dulu, dan dimasukan ke penjara dekat masjid Muhammadiyah. Semua
dibunuh kecuali Pak Jahal,” cerita Kafrawi. [12]
Berbagai peristiwa biadab tersebut, sebetulnya
menjelaskan bahwa pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, bukanlah membela diri
seperti yang digaung-gaungkan Aidit. Jika hanya membela diri mengapa mereka
membantai para kiai dan santrinya yang tak bersalah dan tak ikut dalam konflik,
secara sistematis?
Sumber: Republika