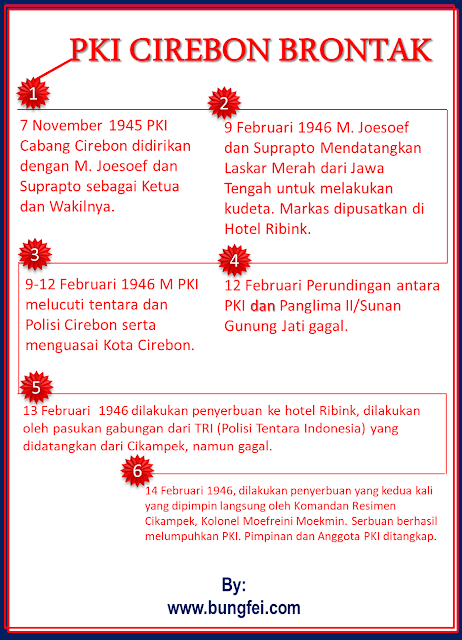19 November 2019
Diskusi internal yang cukup panjang. Dua setengah jam dan belum juga usai. Diskusi internal, yang akhirnya diberi nama oleh Adhe -Tholabul Ilmi- kali ini, dipantik oleh Devananta Rafiq, alumni mahasiswa Ilmu Politik UGM, 2014. Ia mendiskusikan Chantal Mouffe, seorang pemikir politik asal Belgia. Teks ini telah berhasil ia pertahankan dalam ujian, Mei lalu. "Mouffe kupilih ditengah tema skripsi yang itu-itu saja," katanya.
Siang tadi, Rafiq membagikan poin-poin skripsinya kepada saya. Bila berkenan membaca, sila klik tautan berikut:
Ketertarikan personal dengan sejarah Indonesia modern
membawa saya pada pemahaman, bahwasannya pada era 1950 hingga 1965, banyak
sumber pengetahuan yang tidak terdokumentasikan dengan baik.
Hal itu amat disayangkan, karena berdasarkan apa yang
saya arsipkan, geliat intelektualitasnya sungguh meriah dan menyala bernas.
Proyek pengarsipan digital media massa yang saya lakukan
berawal dari inisiatif personal yang tertarik dengan sejarah Indonesia usai
perang kemerdekaan. Berawal dari keisengan ketika membuka lembar-lembar koleksi
pribadi majalah lawas, kemudian berlanjut pada penemuan tulisan-tulisan menarik
yang patut dibaca dan disimpan sebagai sumber pengetahuan.
Yang langsung terpikir saat itu adalah keinginan untuk
mengkliplingnya. Tetapi, bila harus menggunting lembar-lembar majalah itu
sungguh teramat sayang, karena bakal merusak fisiknya.
Sebagai alternatif, memindainya dan kemudian menyimpan dalam
bentuk digital agar bisa dibaca sewaktu-waktu tanpa harus membuka lagi majalah
tersebut.
Kegiatan iseng-iseng ini, lambat laun, ternyata memiliki
banyak faedah. Lembar-lembar koleksi majalah yang merapuh termakan usia tak
perlu lagi acap dibuka sehingga tidak merusak keutuhan fisiknya. Selain itu,
file yang sudah berbentuk digital mudah pula disimpan dan diakses oleh berbagai
pihak yang membutuhkan arsip tulisan itu.
Kegiatan mengarsip dan kemudian membaginya kepada publik
inilah yang menjadi proyek kerja personal saya sebagai individu yang peduli
ihwal pentingnya arsip sebagai sumber pengetahuan --di luar pekerjaan saya
sebagai pelapak daring buku lawas, dengan akun bernama: Tokohitam.
Berkat kegiatan yang mulanya iseng ini, pada September
2017, Tokohitam turut berpartisipasi dalam Festival Arsip IVAA dengan membawa
koleksi digitalnya untuk disajikan dalam kegiatan bernama Bakar Arsip.
Nilai penting
pengarsipan digital
Kegiatan pendigitalisasian koleksi ini lantas memunculkan
kesadaran ihwal pentingnya arsip sebagai sumber pengetahuan. Ketertarikan
personal dengan sejarah Indonesia modern membawa saya pada pemahaman,
bahwasannya pada era 1950 hingga 1965, banyak sumber pengetahuan yang tidak
terdokumentasikan dengan baik.
Hal itu amat disayangkan, karena berdasarkan apa yang
saya arsipkan, geliat intelektualitasnya sungguh meriah dan menyala bernas.
Sebuah era di mana intelektualitas dicatat dan dipublikasikan dengan baik oleh
media massa yang muncul bak cendawan di musim hujan. Itulah sebabnya kemudian saya
lebih banyak memfokuskan diri pada pengarsipan majalah atau media massa yang
terbit di era-era tersebut.
Di era yang sama, banyak pula bermunculan
media massa yang penting untuk diarsipkan. Baik itu majalah yang bertema umum,
seperti majalah Siasat, Mimbar Indonesia, Merdeka, Pesat, Nasional,
Majalah Kompas, Minggu Pagi, dll. Majalah khusus memuat perihal seni budaya,
seperti Majalah Kebudayaan INDONESIA, Zenith, Majalah Seni, Majalah
Budaja, Pujangga Baru, Konfrontasi, Zaman Baru, dll. Bahkan ada majalah yang
khusus memuat karya sastra, terutama cerita pendek, bernama KISAH.
Majalah KISAH menjadi salah satu pionir dalam
mengenalkan tren sastra majalah yang muncul di era tahun 1950-an awal. Tren
sastra majalah pertama kali diperkenalkan oleh Nugroho Notosusanto dalam
artikelnya yang terbit di Majalah Kompas (bedakan dengan harian Kompas)
No. 7, Juli 1954.
Tulisan yang berjudul “Situasi 1954” ini menyoroti
maraknya penerbitan cerpen dan puisi dalam majalah seiring dengan munculnya
perdebatan mengenai krisis kesusastraan Indonesia yang bermutu. Peran Balai
Pustaka kemudian menjadi sorotan karena tidak mampu mengakomodir karya-karya
sastra terbaik yang membuat banyak penulis beralih untuk mengirimkan
karya-karyanya ke berbagai penerbitan majalah yang kemudian mengakibatkan
munculnya karya-karya sastra yang disesuaikan dengan kebutuhan media itu
sendiri.
Pengarsipan media massa ini penting, karena tak banyak
dari media-media itu yang bertahan lama dan keberadaannya kini susah ditemui.
Ada beberapa media massa yang hanya mampu bertahan tak sampai lima tahun.
Mereka harus tumbang karena kekurangan biaya atau karena kalah bersaing dengan
majalah lainnya.
Majalah Zenith misalnya, adalah majalah
kebudayaan yang hanya terbit empat tahun. Dalam Zenith sering saya
jumpai artikel-artikel seni budaya yang menarik untuk diarsipkan, seperti
misalnya artikel Trisno Sumardjo mengenai “Kedudukan Seni Rupa Indonesia”,
artikel karya komponis Amir Pasaribu mengenai beda antara “Musik Nasional dan
Musik Barat”, dll. Zenith, yang perdana terbit pada 1951, mesti tumbang
setelah menelurkan empat nomor pada 1954.
Pascatumbangnya Zenith, muncullah majalah SENI yang
terbit pada 1955. Tetapi, mesti berakhir dalam setahun dengan menelurkan 12
edisi. Majalah ini banyak memuat artikel dan berita-berita di bidang seni rupa.
Saya menjumpai banyak karya rupa yang dibahas dengan genial dalam majalah ini.
Banyak pula majalah-majalah yang kini menjadi barang yang
langka seperti jurnal kebudayaan milik Lekra, Zaman Baru. Awalnya, nama
tersebut dipakai oleh majalah mingguan sosial politik yang terbit di Surabaya.
Lekra, yang saat itu belum punya media massanya sendiri, hanya menumpang pada
rubrik lembar kebudayaan yang beberapa halaman saja dalam majalah
tersebut.
Zaman Baru kemudian bersulih menjadi jurnal
kebudayaan milik Lekra pada 1953, beriringan dengan pendefinisian ulang
Manifesto Kebudayaan Lekra. Dari jurnal inilah saya menjumpai karya tulis
beberapa pesohor lukis di medio 1950-an, seperti Basuki Resobowo dan Batara
Lubis. Sayang, majalah ini mengalami librisida pada 1965 dan berakibat pada
hilangnya rekaman intelektualitas orang-orang Lekra. Hingga kini agak susah untuk
menangkap geliat intelektualitas orang-orang Lekra langsung dari sumber
pengetahuan primernya.
Satu lagi majalah yang penting untuk diarsipkan adalah
Majalah Kebudayaan INDONESIA. Majalah ini terbit perdana pada 1949 dan
diterbitkan oleh Balai Pustaka. Kemudian, pengelolaan penerbitan berpindah
kepada sebuah lembaga kebudayaan bernama Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional
(BMKN).
Majalah ini menjadi penting untuk diarsipkan karena
memuat banyak karya tulis para penggiat kebudayaan Indonesia pascaperang kemerdekaan.
Dibandingkan majalah-majalah kebudayaan lainnya seperti Zenith, Pujangga
Baru, Budaja ataupun Konfrontasi, majalah ini lebih utuh
membicarakan kebudayaan tanpa tendensi yang berat sebelah.
Mutu majalah ini
kemudian merosot tajam di tahun 1960-an hingga kemudian menghilang setelah
menelorkan tiga edisi pada 1965.
Pengerjaan proyek
digitalisasi koleksi
Laku pengarsipan yang saya kerjakan sebenarnya sederhana
sekali. Pada awalnya hanya mendigitalisasi tulisan-tulisan karya sosok
tertentu, sseperti Pramoedya Ananta Toer. Lambat laun, saya asmengarsipkan pula
tulisan-tulisan yang bertema sosial, politik, seni dan budaya yang menurut saya
masih kontekstual untuk dipelajari sebagai sumber pengetahuan.
Dalam perjalanan pengarsipan kemudian saya tidak lagi
hanya mengarsipkan satu persatu tulisan, tapi kemudian jika menjumpai majalah
atau buku yang langka dan layak untuk diarsipkan, saya bakal mendigitalisasi
secara utuh.
Dalam perjalanan pengarsipan, saya sering terkendala
dengan minimnya koleksi yang saya jumpai dan miliki. Selain soal bea, mengingat
pengerjaan proyek ini hanya menggantungkan diri pada pendapatan pribadi sebagai
seorang pedagang buku lawas, juga terkendala pada kian susahnya mendapatkan
koleksi yang layak untuk diarsipkan. Seringkali saya juga menjumpai majalah
atau koran yang memuat artikel yang menarik, tetapi ternyata masih bersambung
dengan penerbitan selanjutnya yang keberadaannya susah untuk ditelusuri.
Akhirnya, arsip itu menggantung dan tidak mampu bercerita
secara detail. Kadang pula kondisi majalahnya sudah terlalu rapuh termakan usia
hingga tak bisa lagi diarsipkan karena bisa dipastikan akan merusak fisiknya
lebih parah.
Selain kendala biaya dan minimnya koleksi, kendala teknis
seringkali menghambat kerja pengarsipan. Saya hanya menggantungkan pengerjaan
pada sebuah mesin pemindai berukuran A4 yang hanya mampu memindai lembaran
berukuran sama, sehingga ketika menjumpai lembaran yang ukurannya lebih saya
harus menyiasatinya dengan menjadikan arsip itu dalam beberapa potongan. Karena
bekerja sendirian, saya juga seringkali cepat merasa lelah dan bosan ketika
terus menerus menghadapi kerja pengarsipan tersebut. Kerja sendirian ini juga
membuat saya lebih banyak mendigitalisasi arsip yang saya senangi saja,
sehingga gampang melewatkan data atau tulisan yang sebenarnya penting.
Pada awal 2019, saya bergandengan tangan dengan seorang
kawan yang aktif dalam bidang penerbitan buku dan mendirikan sebuah rumah buku
yang kemudian kami beri nama O.TH, singkatan dari nama Octopus dan Tokohitam.
Rumah buku ini adalah sebuah perpustakaan, berikut sebuah toko buku dan kantor
penerbitan kecil, yang didirikan untuk menghidupi kerja-kerja harian kami.
Dalam rumah inilah kemudian saya bekerjasama dengan seorang kawan yang
mempunyai hasrat yang sama dalam hal pengarsipan kembali mengerjakan proyek
digitalisasi dengan semangat yang baru. Salah satu proyek yang kini sedang
dikerjakan di Rumah Buku O.TH adalah mendigitalisasi arsip mengenai gerakan
pemuda Indonesia setelah era perang kemerdekaan bersumber pada berbagai media
massa tahun 1950-an yang menjadi koleksi perpustakaan.
Pengerjaan arsip digital gerakan pemuda ini berawal dari
kegundahan kami terhadap banyaknya resistensi masyarakat luas terhadap peran
pemuda dan pelajar dalam kegiatan protes terhadap kerja pemerintah.
Aksi para pemuda pelajar dalam berbagai kegiatan unjuk
rasa dianggap negatif dan kontraproduktif dengan peran mereka sebagai murid
yang harusnya belajar di kelas. Padahal, jika kita memahami sejarah sebagai
alat penimbang kondisi-kondisi yang terjadi di hari ini, maka kita akan
menemukan bahwa apa yang terjadi di hari ini berkorelasi dengan apa yang
terjadi di masa lalu.
Pemeriksaan terhadap koleksi milik Rumah Buku O.TH
memperlihatkan bahwa banyak peristiwa dan kegiatan protes yang melibatkan
pelajar dan pemuda terjadi di era tahun 1950-an. Selain itu, kami menemukan
beberapa artikel yang menarik mengenai peran pemuda dan pelajar dalam gerakan
sosial, yang kini mungkin tak banyak orang bahas atau sampaikan.
Pengarsipan
digital sebagai kerja gotong royong
Kerja pengarsipan adalah sebuah kenyataan yang harus
dijalankan secara berkesinambungan dan konsisten. Membutuhkan banyak energi dan
biaya yang tak sedikit. Sebab itu, kerja bergotong royong adalah solusi
terdepan yang harus ditempuh mengingat banyak dan luasnya sumber yang harus
segera diarsipkan. Berjejaring dengan sesama penggiat arsip digital harus
diperluas beriringan dengan penyebaran kesadaran pentingnya kegiatan itu
sebagai sebuah kerja budaya.
Berjejaring juga tidak hanya bermanfaat ketika sesama
penggiat saling bekerja bersama mengarsipkan sebuah isu yang menarik untuk
ditelusuri, namun juga bermanfaat dalam perburuan arsip atau dokumen yang mulai
susah untuk didapatkan. Perpustakaan-perpustakaan, kebanyakan milik instansi
pemerintah, yang masih banyak menyimpan koleksi majalah atau media massa lama
nyaris tidak melakukan kerja apa-apa untuk menyimpan koleksinya agar mudah
diakses oleh publik. Mereka seringkali mudah melepaskan koleksinya menjadi
tumpukan kertas usang tak berguna yang kemudian diperjualbelikan secara bebas
di pasaran buku langka. Ini sungguh menyusahkan para penggiat arsip digital
ketika kemudian koleksi tersebut jatuh ke tangan pihak-pihak yang lebih ingin
memilikinya sebagai memorabilia, bukan sebagai dokumen atau arsip yang perlu
untuk disebarluaskan sebagai sumber pengetahuan.
Digitalisasi memudahkan para penggiat pengarsipan dalam
pengerjaannya menggunakan sumber daya yang terbatas. Setiap penggiat kerja
arsip digital bisa menggunakan alat yang dia miliki secara maksimal tanpa
menunggu tersedianya alat yang lebih mumpuni. Setiap penggiat juga tak perlu
harus menunggu tersedianya arsip yang istimewa, cukup dengan mengerjakan apa
yang ia temukan dan dirasa menarik sesuai konten yang ingin dipelajari atau
ditelusuri maka kecenderungan untuk terus bertekun diri akan membawanya pada
perjumpaan-perjumpaan yang istimewa, baik perjumpaan dengan sesama penggiat
arsip digital maupun dengan sumber-sumber yang menarik untuk diarsipkan.
Kerja pengarsipan digital bisa dikerjakan secara
individual maupun kelompok tanpa menunggu kondisi yang ideal tersedia. Segala
kendala hanya bisa dipanggul bersama secara bergotong royong. Berjejaring
meluas dan terus berbagi informasi agar pengarsipan digital bisa terus
dijalankan tanpa menunggu semua arsip atau dokumen sejarah musnah akibat
abainya banyak pihak yang seharusnya bekerja maksimal untuk mempertahankannya.
*Ditulis oleh Dodit
“Tokohitam” Sulaksono